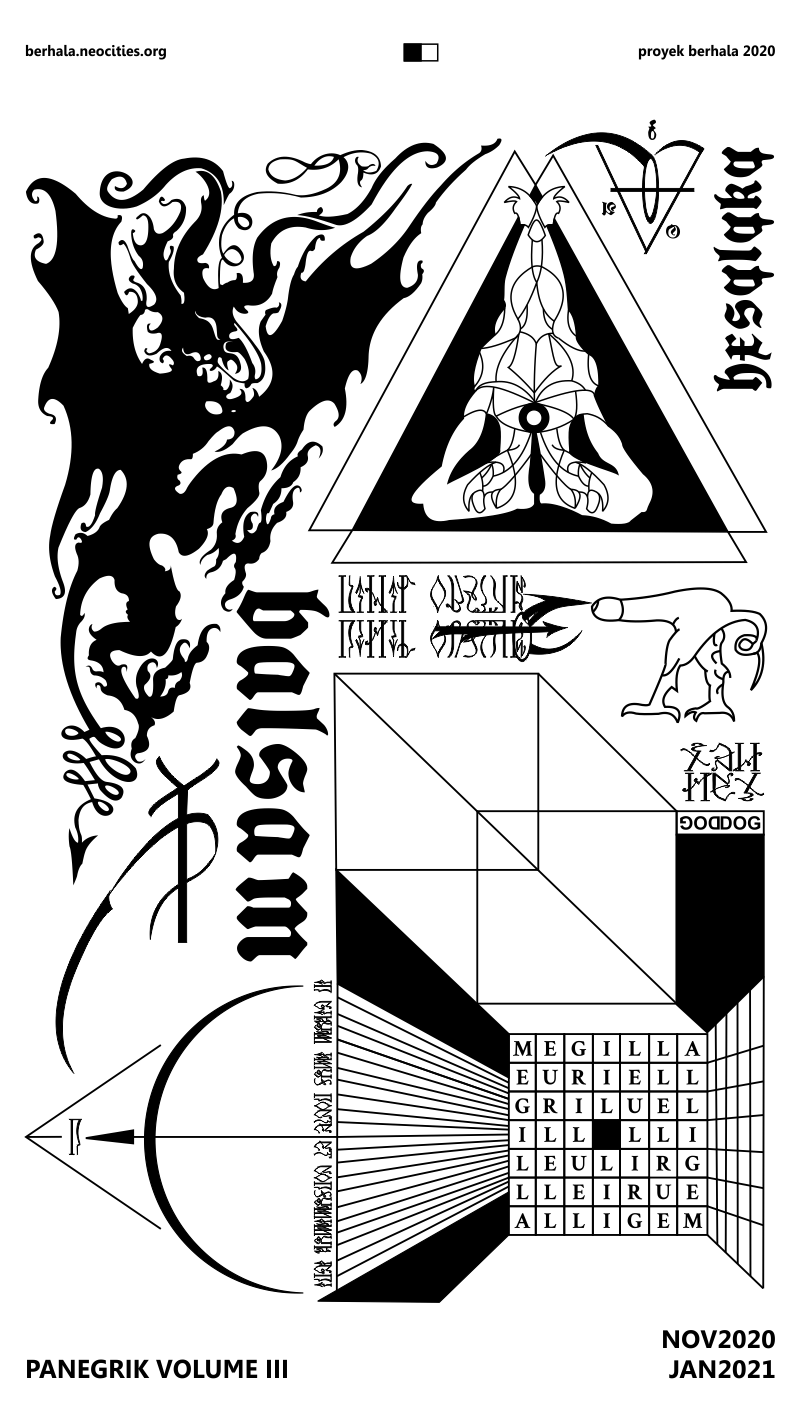
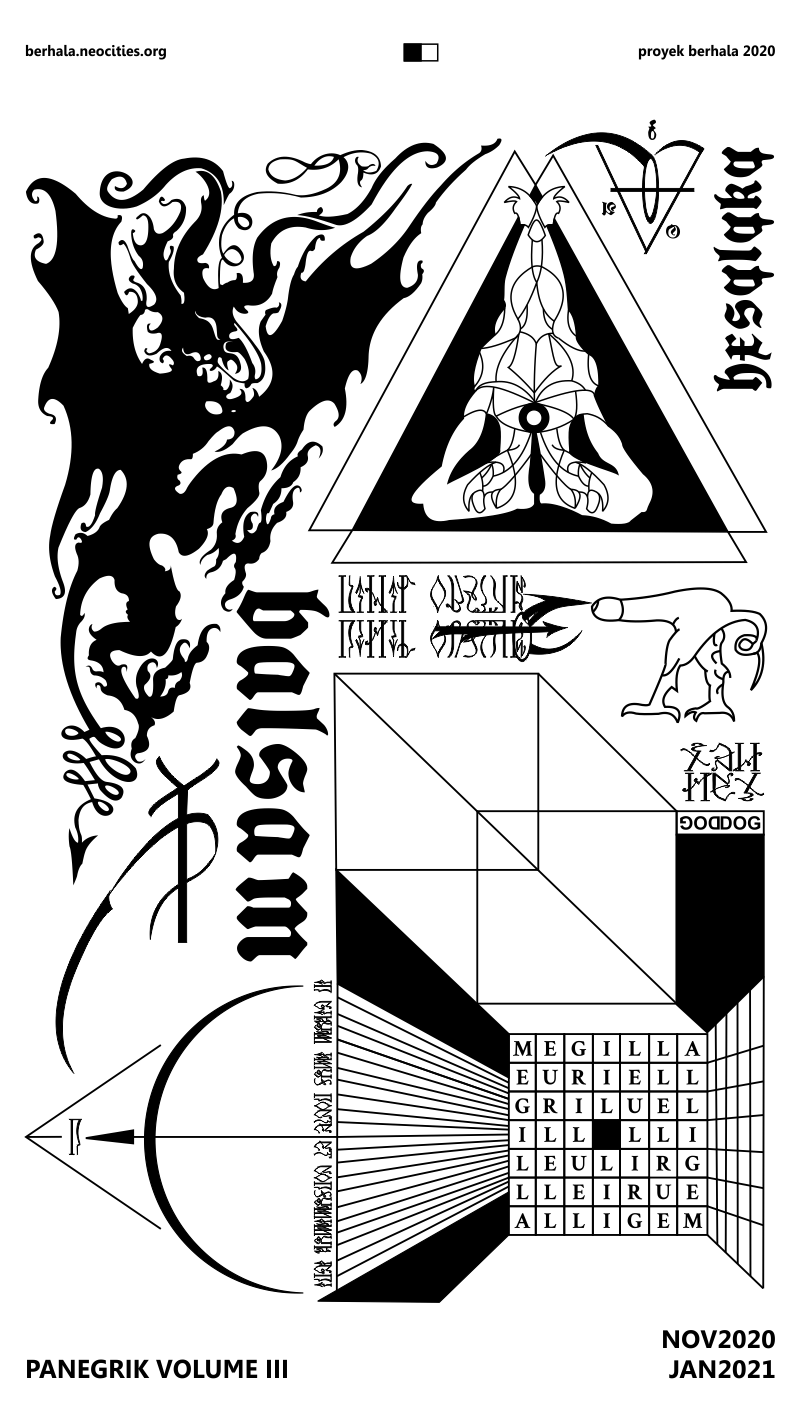
Terbaring di atas karpet ruang tengah, mencengap tersadar, aku masih terengah mencoba mengatur napas saat kudengar pintu terbanting terbuka diikuti suara derap kaki dari kamar sebelah. Limbung, susah payah kuseret badanku mendekati sudut ruangan. Hal pertama yang kupikirkan adalah barang-barang berharga di lemari kamar tidur, terlebih setelah terdengar suara benda-benda berjatuhan saat mereka mengobrak-abrik rak di salah satu sisinya. Kuingat-ingat lagi, lamat kuingat mereka tak mengenakan topeng atau penutup kepala, kemungkinan besar mereka kemari bukan untuk merampok.
Lamunanku buyar ketika terdengar suara katana peninggalan mendiang bapak dicabut dari sarungnya, tajam berdesing menggema melintasi ruangan. Pandanganku mengabur, disusul bayangan sabetan pedang dan kucuran darah segar. Keringat dingin mulai membasahi kening dan tengkukku. Tiba-tiba kuingat lagi perih sayatan pisau di ujung telunjukku saat membantu ibu memasak pada hari besar saat seluruh anggota keluarga kami berkumpul. Sensasi mengerikan itu muncul dibarengi kejutan lain. Jelas kulihat bagaimana pedang itu dilemparkan begitu saja ke ruang tengah, nyaring beradu dengan lantai, lalu salah seorang di antara dua sosok penyusup itu berjalan menuju sofa, tak jauh dari tempatku berada. Duduk di sana, di hadapanku.
Dari tempatnya duduk sekarang, ia pasti dapat menyadari keberadaanku, meringkuk gemetar di bawah bayang-bayang pintu depan yang setengah terbuka. Rambutnya panjang sebahu, perempuan paruh baya itu duduk mengangkang, mengangkat salah satu kakinya dan meletakkannya di atas sandaran lengan sofa. Kulihat ia mengangkat rok yang ia kenakan dan mulai membelai selangkangannya sendiri. Aku tak bisa melepaskan pandanganku darinya, masih tak yakin antara kosong dalam tatapan matanya atau mungkin pula ia melakukannya sembari memperhatikanku. Aku tak tahu pasti, ruangan remang, hanya diterangi lampu duduk di dekat tangga. Aneh sekali, entah kenapa kubayangkan wajahku sendiri saat menyaksikan wajah perempuan itu, bagaimana kening dan pipiku berkerut-kerut saat aku onani.
“Tak ada waktu lagi,” tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar sebelah.
Perempuan itu pun menengok memalingkan wajahnya dariku ke arah rekannya, seorang pria muda yang seketika menggenggam lengan kirinya dengan kasar lalu membanting perempuan itu ke atas meja pendek di tengah ruangan. Permukaan kacanya keras beradu dengan punggung perempuan itu, tetapi tak pecah. Tidak sebelum akhirnya pria itu menghentakkan kaki kanannya ke atas meja, mencekik leher perempuan itu dengan lututnya.
“Aku hanya ingin melakukannya saja,” ucap perempuan itu lembut di antara napas tersengal sesak.
“Kamu selalu menginginkannya saat aku tak ingin melakukannya sama sekali, perek sialan!” Lelaki muda itu mengangkat kakinya lalu duduk berlutut, mengganti cekikannya dengan telapak tangan kanannya yang gempal. “Jangan sakiti aku terus seperti ini dong, aku mohon! Bajingan!” ucapnya setengah berteriak, menekankan setiap katanya dengan membentur-benturkan kepala perempuan malang itu ke atas meja. Tubuh kurusnya bergetar, menjawab irama yang didiktekan tangan pria muda itu kepadanya.
Selama beberapa menit kemudian, keduanya hanya diam saling berpandangan.
Aku bisa menyaksikan dengan jelas bagaimana keringat membanjiri permukaan kulit kuning langsat perempuan itu, bagaimana darah begitu deras mengaliri pembuluh darahnya, merah dan biru yang tampak bisa meledak kapan saja dari permukaan lengan dan kakinya.
“Kamu harusnya paham betul soal hal ini.” Sentak pria itu sembari melepaskan cekikannya, berdiri, lalu berjalan berkeliling ruangan sembari menghentak-hentakkan kakinya.
Dengan putaran yang begitu elegan, perempuan itu bangkit dari tempatnya terbaring. Hanya dalam sekejap, ia tiba-tiba menempelkan wajahnya di hadapan wajahku. Berdiri membungkuk, menyeringai, membuyarkan ribuan pertanyaan yang bergolak memenuhi kepalaku, seolah menegaskan kepadaku bagaimana ia sepenuhnya sadar bahwa sedari tadi aku menyaksikan semua yang telah terjadi. Bila sebelumnya setiap gerak tubuhnya terkesan begitu lambat dan ambigu. Kini setelah menghukumku sebagai seorang penonton, bisa kurasakan bagaimana kesemuanya dengan tegas menampakkan ekspresi kesenangan atau bahkan kebahagiaan.
“Kamu menikmatinya bukan? Lonte! Sinting! Edan!” Bentak pria itu lagi sembari memeluk perempuan itu dari belakang. “Tidak denganku, aku melakukan semua ini untuk kita, untukmu seorang.” Ia kemudian melepaskan pelukannya dan memerintahkan perempuan itu untuk duduk di lantai.
“Aku tak sepertimu,” jawab perempuan itu, lebih terdengar seperti penyesalan yang dia ucapkan untuk dirinya sendiri alih-alih sebuah permintaan maaf. “Coba lihat,” lanjutnya, mengundang pria itu mendekat, menunjukkan luka segar serta memar di sekujur lengan dan sikunya. Merah menggelap seolah tangan gempal pria itu masih menarik besi dalam aliran darahnya layaknya magnet.
“Perhatikan lagi, kesemuanya begitu jelas, begitu nyata. Lihat lagi, kesemuanya terasa sepertimu, seperti kasih dan sayangmu padaku.” Lanjut perempuan itu dengan penuh emosi.
“Gila! Aku tak pernah membayangkannya sejauh ini sebelumnya, oke...Aku...Bisa saja membunuh. Mudah saja, itulah hal pertama yang kupikirkan sesampainya di sini.” Jawab pria itu, kali ini terbata-bata, sembari memelototi katana yang tergeletak tak jauh dari kakinya.
Badanku seketika terasa tak bisa digerakkan lagi. Entah apa yang sedang terjadi, bagaimana aku bisa mengalami semua ini. Kucoba mengingat kembali bagaimana semua ini bermula, tetapi tak bisa. Aku hanya bisa pasrah, sesekali memejamkan kedua mataku, tak mampu mengusir perasaan ngeri dari pikiranku.
Masih duduk di lantai, perempuan itu menggeser badannya, kembali mendekat ke arahku. “Bayangkan Sayang, memotongnya sedikit demi sedikit, menyayatnya pelan-pelan. Kematian menari menemanimu, terus berada di dekat tubuhmu…”
“Ya, mati dengan seribu sayatan. Lingchi. Aku masih ingat, bagaimana aku bisa lupa, kamu menceritakannya berulang kali dengan antusias setiap kali kita bertemu.” Ucap pria itu memotong perkataannya.
“Ya, maksudku, kesemuanya bisa berlangsung selama beberapa hari... Atau mungkin beberapa minggu... Menunggu datangnya mati dalam penantian panjang tak berujung, tak ada pilihan selain mengingat kembali dosa-dosamu sepanjang hidup dalam usaha sia-sia untuk mematikan kesadaran dan melawan rasa sakit.”
“Setiap sayatannya mengalihkanmu dari sayatan dan tusukan yang kamu peroleh sebelumnya.” Lanjut pria itu menimpali.
“Aku membayangkan bagaimana prosesi itu mengulitimu perlahan, menampakkan daging di sekujur tubuhmu.” Kata perempuan itu, “Akan tetapi, kali ini berbeda. Bisakah kamu menyayat dirimu sendiri?”
“Aku takkan melakukannya! Aku takkan mengikuti semua kemauanmu begitu saja! Anjing betina terkutuk!” Balas pria itu, kembali berteriak penuh emosi.
“Bukan begitu, Sayang. Sorry, maksudku, sekedar bertanya… Seumpama saja.”
Pria itu sejenak terdiam, kembali mondar-mandir berkeliling ruangan. “Aku yakin aku tak mungkin melakukannya. Aku takkan bisa, bagaimana denganmu?”
“Aku. Ah, aku pun tak yakin, tetapi mungkin saja. Kamu tahu? Konyol sekali membiarkan orang lain melakukannya untukmu, pasti beda, rasanya.” Ucapnya sambil menurunkan roknya, seolah mencoba menghindarkan kulit telanjangnya dari sentuhan karpet. “Jangan bohong, buat apa menipu dirimu sendiri. Aku tahu kamu pasti bisa melakukannya, ingin melakukannya, ingin merasakannya.”
“Cukup! Anjing! Kontol! Memek! Bajingan!” Pria itu kembali berteriak sekencang-kencangnya.
Aku ingin sekali menghilang, setidaknya berlindung lebih jauh dalam bayang-bayang pintu yang menyelimuti kedua kakiku sekarang, sebisa mungkin mengalihkan perhatian mereka dariku. Akan tetapi, menggerakkan jari pun aku tak kuasa. Perih, lelah, dan pening mengikatku kencang dengan muram remang-remang ruangan ini.
“Oke. Ini semua… Aku ingin kamu bisa merasakannya, aku…” Pria itu menanggalkan kausnya, “Lihat lagi,” ucapnya sembari menunjukkan dadanya yang dipenuhi bercak-bercak putih pucat, “Kulit mati, kebal dari segalanya, mati rasa.”
Pria itu sejenak terdiam dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arahku. “Lihat, dia kencing di celana.”
Sekejap saja, mereka berdua tiba-tiba berdiri di atasku, kulihat perempuan itu menenteng katana yang sebelumnya tergeletak di tengah ruangan.
“Ya, aku tahu, Sayang.” Ucap perempuan itu, tampak puas dengan apa yang baru saja ia lihat. Aku tak mampu menggerakkan leherku untuk menengok cukup jauh ke arah kakiku, entah bagaimana rupa celana yang kini aku kenakan. Berulang-ulang terputar dalam kepalaku, bagaimana hangat air kencing menjalari pahaku.
“Ayo bangun!” Perintah pria itu padaku. Aku mencoba lagi menggerakkan badanku, tetapi sia-sia.
Keduanya kemudian mencoba mengangkat badanku, tetapi gagal. Aku hanya terbaring diam, menantikan apa lagi yang mereka lakukan padaku.
Perempuan itu kembali mendekatkan kepalanya ke arahku, “Sebentar lagi mungkin ia akan mati, napasnya putus-putus, hahahaha, kasihan juga.”
Aku tak yakin lagi. Kesadaranku terus timbul dan tenggelam. Kali ini bisa kulihat kausku robek terbuka, perempuan itu memainkan jari-jarinya mengikuti guratan luka dan memar di permukaan perut dan dadaku. Lengan kurusnya muncul dan menghilang begitu saja dari penglihatanku. Setiap kali aku menyaksikan jemarinya, ada sensasi yang kurasakan, mengikuti gerak tangannya yang berputar-putar di atas tubuhku. Kulihat ia mengulurkan kedua tangannya ke arah wajahku saat tiba-tiba badannya ditarik menjauh. Kedua bahunya membentur tembok terlebih dahulu, diikuti bagian belakang kepalanya.
“Apa yang kalian inginkan dariku?” Pria muda itu pasti bisa mendengarnya dengan jelas, meski aku sendiri tak yakin seberapa keras aku mampu berucap. Ia berlutut di sebelah badanku. Aku bisa menyaksikan kepalan tangan kanannya meluncur menghantam wajahku, pukulannya memaksa kepalaku menengok ke kanan, menenggelamkannya dalam-dalam ke lantai, menyaksikan perempuannya terduduk gemetar bersandar di dinding. Tak pernah sebelumnya kulihat tubuh yang mengundangmu untuk melukainya, untuk meremuknya sampai hancur, seperti tubuh perempuan itu. Aku coba mengamatinya baik-baik, memperhatikan luka di sekujur tubuhnya dan membandingkan dengan apa yang mungkin terjadi pada tubuhku saat ini.
Perempuan itu merangkak mendekat, menghadapkan kepalaku ke atas lalu berjongkok mengangkangi kakiku. Ia menarik celanaku ke bawah, mengusap-usap penisku sebelum menjilatinya dan memasukkannya ke dalam mulut. Aku tak tahu lagi, sepertinya kelaminku sudah cukup keras saat ia mulai menyetubuhiku.
Pandanganku berulang kali kembali gelap mengabur, kali ini kulihat sebuah sayatan segar di pipi kanannya, darah mengalir keluar menyusuri leher dan masuk ke dalam gaun hitam yang ia kenakan. Sesaat kemudian kepalanya tertunduk, diam tak bergerak, masih tegak duduk di atas selangkanganku.
“Lakukan saja semua yang kuperintahkan kepadamu, aku mohon,” untuk pertama kalinya kudengar suaranya pecah serak hampir terisak, “sama sekali tak mudah menceritakannya kembali padamu.” Pria itu menarik napas panjang lalu terbatuk, “Sulit rasanya, sakit, aku pun sakit. Kau tahu tidak?” Ada keraguan dan jeda panjang sebelum ia kembali berbicara padaku, “Dia jauh lebih baik darimu, dibanding semua orang di luar sana. Brengsek!”
“Kenapa?” Aku tak tahu lagi, pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutku, aku tak tahu harus berkata apa setelah semua yang kualami.
“Tak ada kenapa baginya atau bagiku. Perempuan ini adalah aku sendiri…” Perkataannya terpotong saat ia membuka kancing dan resleting celananya. Berlutut di samping kepalaku, mengeluarkan penisnya dan menggesekkan ujungnya di atas luka pada kening dan kelopak mataku.
“Kau tahu? Sudah sewajarnya kau mencintai apa yang kau ciptakan sendiri.” Ucapnya sambil memukul-mukulkan tangan kirinya pada bercak-bercak putih di permukaan dadanya. Pria itu menarik rahangku, memaksa mulutku terbuka dan memasukkan penisnya ke dalam mulutku. Ia menjambak rambutku dan menggerak-gerakkan kepalaku untuk memuaskan ereksinya.
Pening, perih, hanya itu yang kurasakan saat perempuan itu kembali hadir dalam persepsiku. Kali ini ia menggenggam katana dengan kedua tangannya, mengarahkannya ke leher pria itu lalu menarik ujungnya ke belakang seolah hendak mencekik pria itu—saat ia kembali menggoyangkan pinggulnya, mengangkatnya naik dan turun menyetubuhiku. Kulihat kedua matanya membengkak sebesar bola pingpong, pasti mataku pun demikian, perasaanku campur aduk saat memperhatikan air mata keluar begitu deras menuruni kedua pipinya.
Aku mencoba mengenali nafsu dan gairah dalam ekspresi wajah perempuan itu, tetapi yang kutemukan hanyalah rasa sakit, senada dengan darah yang menetes dari ujung katana dalam genggaman tangan kanannya.
Pria itu membungkukkan badan dan melepaskan diri dari cekikan katana yang meninggalkan bekas merah di tenggorokannya. Gerakan badannya menghujamkan penisnya lebih jauh ke dalam kerongkonganku. Aku ingin muntah.
“Coba perhatikan dirimu sekarang, aku tak menikmatinya sama sekali.” Kata pria itu. “Jangan sampai dia melihatku,” lanjutnya.
“Pukul saja aku lagi. Hahaha. Ayo pukul!” Balas perempuan itu.
“Bangsat!” Pria itu pun berdiri dan berjalan menjauh. Ia kembali dengan sebuah bantal dari kamar sebelah dan menempelkannya ke atas wajahku. “Ini kan yang kau mau?” Entah pada siapa ia berkata, lamat bisa kudengar teriakannya dari balik bekapan bantal. Basah, lengket kembali menjalari selangkanganku, entah apa pun itu. Lirih, kudengar perempuan itu tertawa cekikikan.
“Masih belum yakin kalau ini yang kau inginkan. Ha?” Bentak pria itu lagi, masih bisa kukenali suaranya, berat bergetar dari bawah bantal.
Aku bisa merasakan jemari kurus perempuan itu bergerak-gerak menggerayangi perutku, mengoles-oleskan cairan lengket di permukaan kulitku.
“Ya, aku tahu! Aku menginginkannya! Aku sangat menginginkannya sejak dahulu! Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku, kucoba berteriak sekuat yang aku bisa pada bantal yang membekap wajahku.
Kucoba bangun dan menggerakkan badanku, tetapi dalam sekejap kesemuanya berubah menjadi perjuangan mempertahankan napas, sampai akhirnya kurasakan dingin terhujam menembus badanku. Aku sendiri tak yakin pada bagian mana. Setiap perih dan sakit berdesir menyebar ke sekujur tubuhku dalam satu tarikan napas. Gelombang besar berdatangan tanpa henti, sensasi demi sensasi, sampai akhirnya hal terakhir yang bisa kuingat hanyalah dorongan hebat dari selangkanganku, hangat yang menjalari luka di sekujur tubuhku.
Pertunjukan macam apa ini? Ah, ide busuk yang sama sekali tak menarik. Pepohonan tampak seperti adas dan kurap sementara rerumputannya pun mati kering. Dada kita hancur lebur, kayunya diolah menjadi lubang berapi.
Kami merencanakan sebuah pesta besar, sukacita empat puluh hari empat puluh malam, kesia-siaan lain untuk setiap kesia-siaan di seluruh dunia.