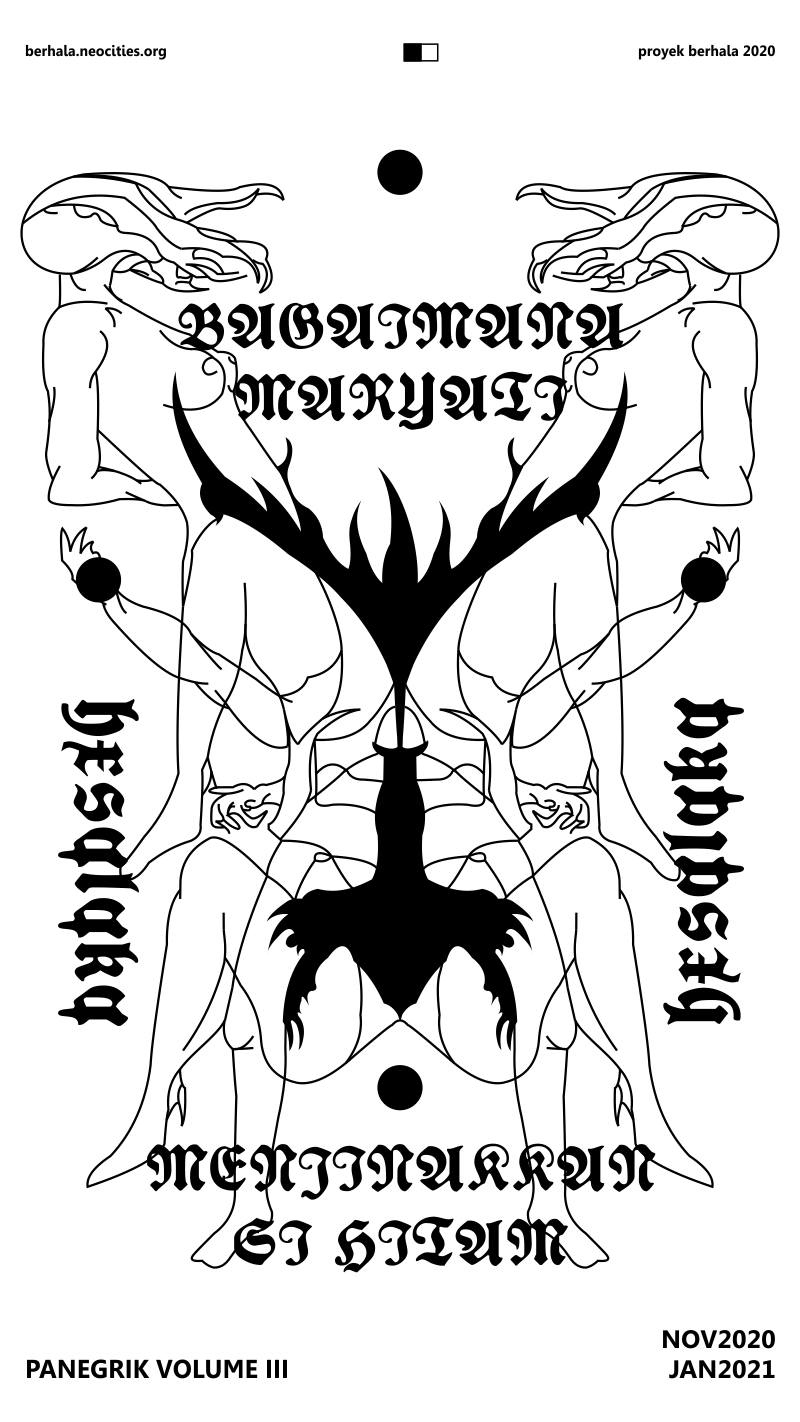
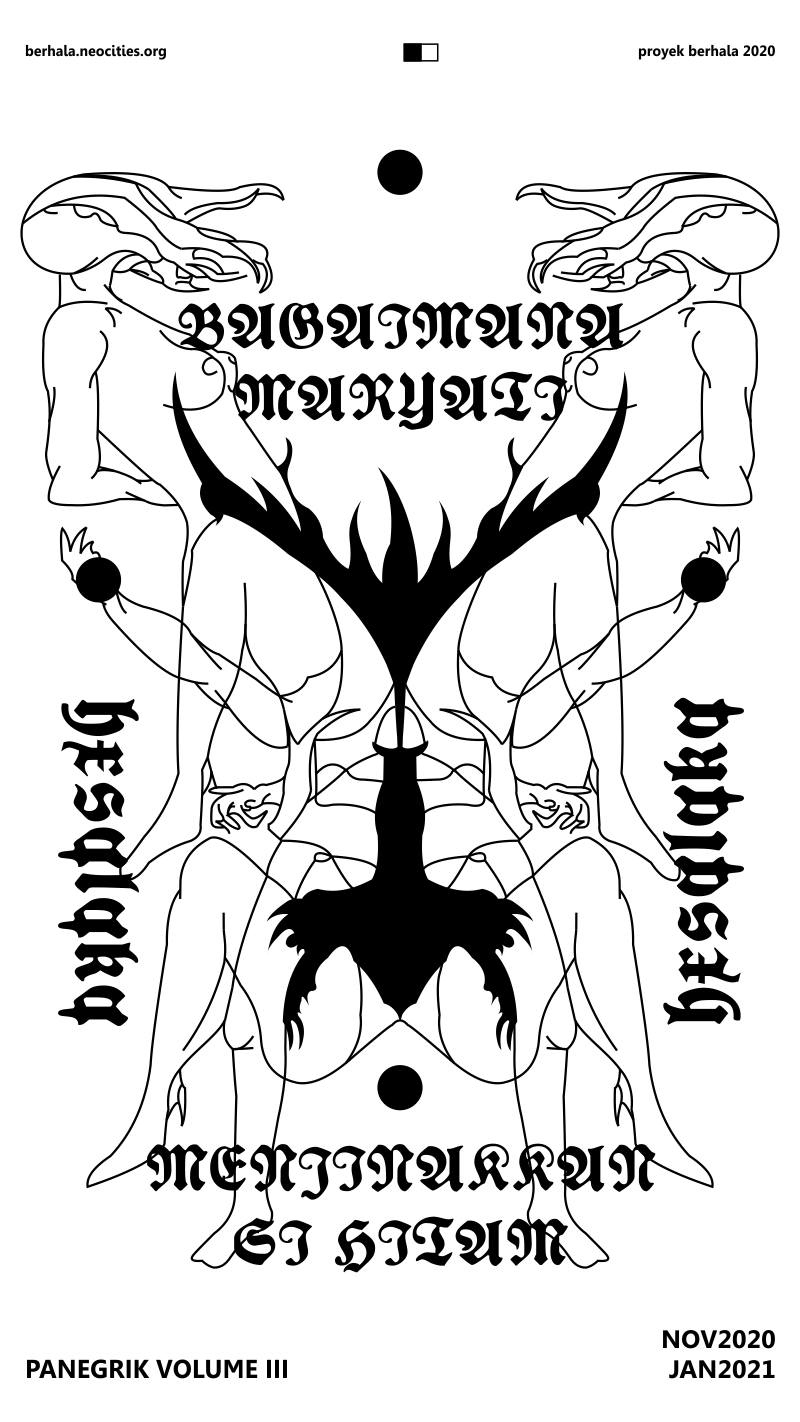
Sebuah prinsip, atau mungkin lebih tepatnya, identitas personal yang tak terpisahkan dari pribadi Maryati, seumur hidup ia tak pernah menyebut segala macam tumbuhan liar sebagai gulma. Ia pun selalu menahan diri untuk tak melabeli sesuatu sebagai baik atau buruk, apa pun itu. Harta paling berharga miliknya sepetak tanah dan rumah kecil di ujung kampung, tepat bersebelahan dengan rumah anak semata wayangnya. Kampung miskin itu terbentang memanjang dihimpit jalan tol serta komplek niaga dan perkantoran, kumuh menyempil di tengah laju dan tersendatnya pembangunan oleh keruwetan birokrasi serta pergulatan politik mengejar keuntungan.
Bagian depan rumah Maryati dipenuhi semak dan rerumputan, begitu lebat sampai-sampai sebagiannya tumbuh merambati dinding batu bata yang baru ia bangun tiga tahun lalu dengan bantuan pemerintah, menggantikan anyaman bambu yang habis dimakan rayap, seperti ingatannya pada suami yang minggat meninggalkannya begitu saja bersama gadis ayu dari kampung sebelah. Rumahnya tak tuntas dibangun, menyisakan tembok tanpa plester dan dapur berlantai tanah, dana bantuan konon katanya berulang kali disunat dalam perjalanannya menuju tangan menantu Maryati yang sehari-harinya bekerja menjadi tukang ojek menghidupi dua orang anak, satu istri, serta mertua semata wayangnya itu.
Hampir setiap sore Maryati keluar rumah lalu duduk di teras, mengamati kucing-kucing liar yang bertengger di atas pagar tanah pemakaman umum tepat di depan rumahnya. Kucing-kucing itu kerap memandangi Maryati, duduk di atas lincak bambu menyesap teh panas sembari menikmati pisang goreng, singkong rebus, atau apa pun yang dihibahkan anak perempuannya padanya. Maryati kadang mendekat ke pagar, menjentikkan jari, bersiul-siul semampu ia bisa, atau menirukan suara mengeong untuk menarik perhatian kucing-kucing liar itu.
Dari belasan yang kerap mampir di sana, ada seekor kucing hitam yang paling menarik perhatiannya, kucing yang paling sering muncul dan biasa berlama-lama tidur di atas pagar itu. Kucing hitam itu kadang memenuhi panggilan Maryati, berjalan berputar-putar mengelilinginya sambil berdesis menyeringai. Suatu sore, Maryati memutuskan untuk berkawan dengan kucing hitam itu, meletakkan sepotong ikan asin beralaskan daun pisang di teras rumahnya.
Lalat-lalat terbang berputar-putar dan hinggap di mana pun mereka mau, selalu datang berduyun-duyun bersamaan dengan musim mangga atau jambu. Bagaimana kalau lalat-lalat itu mengenakan kaus oblong, berkerumun bergerombol macam kuli bongkar di pangkalan kontainer. Bayangkan saja bila kucing-kucing yang setiap sore nongkrong di pagar pemakaman itu masing-masing membawa uang, tak perlu banyak-banyak, per ekor dua ribu rupiah saja. Alamak, tentu saja Maryati pernah sedikit pun berpikiran semacam itu.
Setiap siang Maryati dengan telaten menyedekahkan kudapan buat Si Hitam di teras; ikan asin, daging ayam suwir, kadang lengkap dengan nasi yang disiram dengan sedikit minyak jelantah. Kucing itu pun mulai nyaman merebahkan badannya di teras Maryati, berjalan berjingkat berputar-putar di teras depan sambil melirik penuh curiga ke dalam rumah perempuan itu.
Kala itu Si Hitam terbaring malas di depan pintu, dengan cekatan Maryati mencengkram badannya dan memasukkannya ke dalam kandang kawat yang pekan lalu ia beli di loakan. Sepi, anak perempuan Maryati mungkin sedang ngerumpi di warung atau mengajak anaknya berkeliling kampung naik sepeda, tak ada seorang pun yang sempat mendengar jerit perlawanan Si Hitam mengeong-ngeong liar berusaha keluar dari kandangnya.
Penghujung kemarau di daerah itu selalu sama, bahkan semakin kejam pada setiap kedatangan berikutnya. Ada ritme konstan, gigitan, tepukan, umpatan, sumpah, serapah, semburan ludah, tetes keringat mengalir menuju sudut mata menambah perih dan rasa dongkol yang menggelegak dalam dada bersama raung mesin dua puluh empat jam nonstop dari tol sebelah. Sama sekali tak ada tempat untuk bersembunyi dari hawa panas maupun gejolak kehidupan di kampung Maryati. Saat ia mencengkram perut Si Hitam dan menjejalkan tubuh kurusnya ke dalam kandang, lolongan kucing malang hampir tak terdengar, tenggelam ditelan udara di sekitar mereka berdua. Atmosfer daerah itu sudah tersaturasi sedemikian rupa oleh kerasnya pergulatan bertahan hidup, tak ada lagi kepedulian sedikit pun atas kegilaan yang sore itu terjadi di teras Maryati. Sungguh kontradiktif, kampung itu memendam paradoks yang jauh lebih tua dibanding bangunan-bangunan megah di sisi-sisinya. Berpikir, melata, berdiri tegak, atau berkaki empat, setiap penghuninya harus bisa mempertahankan sisi buas dan liar mereka untuk bisa mengenali daerah itu sebagai rumah.
Rumah adalah sesuatu yang tak terdefinisikan dalam benak Maryati, sebuah konsep yang tak sepenuhnya ia pahami bahkan sampai menua dan memiliki dua orang cucu. Suatu kali abahnya bekerja jadi kuli lepas pemasangan rel kereta, pernah pula proyek pembangunan rumah sakit, belasan proyek lain yang Maryati sendiri tak ingat lagi, hingga akhirnya abahnya menjadi anggota tetap dari rombongan tukang batu yang dikepalai kakaknya sendiri dan kembali ke gubuk kecil di sepetak kebun yang kini ditempati Maryati. Abah menempatinya bersama istri serta tujuh orang anak mereka. Maryati adalah anak nomor tiga, saudara-saudaranya sebagian sudah mati, ada pula yang merantau atau sukses membeli tanah di kampung lain tak jauh dari tempatnya tinggal sekarang. Dari gubuk gelap, kediaman kerabat, pinggiran ruko, sampai akhirnya menikah, melahirkan anak perempuannya, dan ditinggal suami; sendiri menempati rumahnya saat ini, begitulah Maryati mengenali rumah di sepanjang perjalanan hidup yang tak terlalu mengesankan bagi orang-orang seumurannya yang lahir dan tumbuh besar di kota itu.
Maryati tak pernah ingat lagi kawan-kawannya semasa kanak-kanak. Yang ia ingat hanya masa-masa bermain bersama saudara-saudaranya. Mencari segala macam buah, di dekat mereka tinggal atau di perkampungan sebelah. Menangkap kadal atau kodok, berburu jangkrik atau burung gereja, keluyuran sampai menjelang magrib di kebun dan rawa-rawa. Saat terbayang wajah galak emak memanggil mereka untuk segera pulang, Maryati dan saudara-saudaranya pun akan melepas kembali tangkapan mereka, di pematang, di pinggir jalan, atau di dekat kediaman mereka, di mana pun lokomotif rupiah membawa abah dan keluarganya memburu sesuap nasi. Lain cerita bila saudara-saudara lelaki Maryati kebetulan menemukan burung puyuh atau ayam liar, sebelum sore pun mereka akan bergegas pulang dan menyerahkannya pada Emak untuk dimasak.
Mak, bolehkah kami pelihara? Sekali waktu, Maryati dan saudara-saudaranya membawa seekor kelinci dalam kardus, Maryati sendiri merengek berjanji akan merawatnya dengan baik dan meminta Abah membuatkan kandang untuknya. Emaknya hanya berkacak pinggang, menggelengkan kepalanya dengan wajah garang, menunjuk kuali miliknya di dapur dengan dagunya yang lancip lalu memerintahkan Maryati untuk segera mandi karena hari sudah sore. Menurut Emak, anak-anaknya tidak boleh cengeng, ia sering kali mengajak anak-anaknya menyembelih ayam, atau membersihkan ikan hasil pancingan Abah, mereka harus bisa melakukannya bila ingin bertahan hidup. Malam itu seluruh anggota keluarga tampak sumringah menyantap semur istimewa, kecuali Maryati yang memilih untuk menyendiri di ujung dipan, meringkuk menahan tangis sampai akhirnya terlelap.
Satu pelajaran penting yang diajarkan Emak pada Maryati yang tampaknya gagal ia mengerti adalah bahwa segala yang liar sebaiknya dibiarkan terus liar. Hal terbaik yang bisa kita lakukan pada kucing liar adalah mengabaikan mereka, saat dirimu menemui seekor yang menurutmu imut-imut ataupun sedang sakit, biarkan saja.
Tak ada yang tahu pasti kenapa Maryati, di usianya yang tak muda lagi, merasa membutuhkan binatang peliharaan, terlebih-lebih memungut salah satu dari puluhan makhluk liar penghuni kampung itu. Semoga tuhan memberkati kebaikan hati Maryati. Akan tetapi, sudah dua minggu Si Hitam tinggal bersama Maryati dan tetap saja seganas hari pertamanya dimasukkan dalam kandang yang kini berada tak jauh dari pintu kamar mandi Maryati.
Si Hitam tak pernah ragu mengemukakan pendapat atas hubungannya dengan Maryati, mendesis meraung-raung setiap kali tangan Maryati terulur memasuki kandang kawat bersama ikan asin.
Maryati pun sempat berpikir untuk melepas kembali Si Hitam, mungkin ia akan kembali, mungkin ia akan menghabiskan waktu di atas pagar depan rumahnya seperti biasa. Tidak. Tidak mungkin seperti itu. Mungkin Si Hitam takkan pernah kembali lagi, lagi pula Maryati pernah mendengar bagaimana salah seorang tetangganya memungut seekor kucing liar dan dalam dua bulan ia bisa menjadikannya binatang peliharaan yang menyenangkan.
Akan tetapi, Maryati mungkin tak pernah tahu, sebagaimana ia tak pernah terlalu memikirkan hidupnya sehari-hari, bahwa binatang-binatang pun tak jauh berbeda dengan manusia. Semakin tua, semakin sulit pula meninggalkan kebiasaan hidup mereka. Maryati tak pernah sekali pun mendengar pepatah bahwa akan jauh lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada seekor kucing liar masuk rumah lalu bisa betah menempatinya.
Setiap siang Maryati mengeluarkan Si Hitam dari kandangnya dan mengurungnya di dalam kamar mandi bersama kudapan makan siangnya. Si hitam pun tak punya pilihan selain menghabiskan apa yang sudah dihidangkan majikan barunya, melepas kekesalannya dengan menggesekkan badan di seluruh penjuru kamar mandi dan mencakari pintunya. Ritual itu terus dilakukannya sampai menjelang sore dan ia akhiri dengan lolongan panjang berisi doa-doa dan kutukan atas nestapa yang memenjarakannya.
Menantu Maryati yang sempat mengunjungi rumahnya untuk menyerahkan jatah beras bulanan pun kebetulan menyaksikan penderitaan Si Hitam. Ia mencoba meyakinkan mertuanya bahwa ia pernah mendengar fakta unik mengenai kucing liar dari juragannya yang merupakan seorang sarjana. Semakin jauh jarak kelahiran seekor kucing liar dari nenek moyang domestik terakhirnya, katakanlah ia merupakan keturunan generasi keempat atau kelima, maka akan semakin liar pula kucing tersebut. Namun, tak peduli seberapa pun banyaknya generasi yang terlahir liar, mereka akan tetap bergantung pada kebaikan manusia dan sampah yang mereka hasilkan. Tanpa itu, sebagian besar kucing liar akan mati pada tahun pertama kehidupan mereka. Meski begitu, entah karena dendam atau apa, sebagian besarnya akan tetap ganas dan sulit dirumahkan.
Tak banyak yang berubah minggu berikutnya, tak peduli seberapa pun banyaknya porsi ekstra yang diberikan Maryati pada Si Hitam.
Sama halnya kucing-kucing lain pada umumnya, Si Hitam pasti takkan ragu menggerogoti daging Maryati bila saja ia mati. Sayang sekali, fantasi makan besar tersebut sama sekali tak mengurangi rasa bencinya pada tempat terkutuk yang kini ditempatinya. Setiap kali ia dikurung di kamar mandi, ia akan mengasah kuku-kukunya pada pintu dan menunggu kesempatan untung menyelinap melarikan diri bila ada kesempatan. Ia selalu berdoa dengan tulus menunggu datangnya kesempatan itu, mengeong-ngeong sepenuh hati, menyesali kecerobohannya sendiri. Meratap ia memikirkan tikus-tikus yang kelak bisa ia buru sesuka hati di surga para kucing bila ia gagal meraih kemerdekaanya kembali.
Maryati sendiri pun sebenarnya mulai gemas menyaksikan perangai Si Hitam yang tak kunjung melunak. Berdoa siang dan malam pada tuhan dan dewa-dewa yang pernah ia kenali, hingga akhirnya suatu pagi ia memperoleh ilham yang dinanti-nantikannya beberapa minggu terakhir ini. Mandi. Ya, mandi. Maryati selalu ingat bagaimana dahulu ia dan keluarganya selalu mencari-cari tempat mandi selama mengikuti Abah bekerja di berbagai daerah. Hari ini, ia akan memandikan Si Hitam. Mandi adalah penanda bagi segala yang beradab, mandi adalah salah satu ritual penting dalam kehidupan domestik.
Si Hitam seketika meraung saat kandang yang ditempatinya diangkat Maryati, tak seperti biasanya, kali ini majikannya tak mencengkram tubuh kecilnya dan mengeluarkannya dari kandang, pasti hal ini bukan pertanda baik. Ia mengeong makin kencang saat kandang yang ditempatinya diletakkan maryati di lantai kamar mandi. Mendesis, punggung Si Hitam melengkung saat tangan Maryati masuk ke dalam kandangnya, mencakar sebisanya sampai akhirnya tangan gemuk itu berhasil mencengkeram tubuhnya.
Kerepotan menahan kucing itu meronta tak karuan, Maryati menempelkan tubuh Si Hitam ke bibir bak mandi, menggunakan tangan kirinya untuk mengguyurkan segayung air ke tubuh Si Hitam yang masih tak mau berdamai dengannya.
Guyuran demi guyuran, Maryati sesekali mengusap-usap badan Si Hitam yang masih tetap meronta mencakarinya. Perih, gemas, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Perlahan Maryati membenamkan tubuh kecil Si Hitam ke dalam bak mandi, mengangkatnya sekali dan membenamkannya kembali. Sampai seluruh badannya basah kuyup oleh dingin kematian, Si Hitam tetap tak menyerah, mengeong dan mengeong, mendeklarasikan kesetiaannya pada tuhan dan dewa-dewa di langit. Meraung memanjatkan doa terakhir, berharap bisa terlahir kembali menjadi kucing liar atau seekor harimau gagah, berharap bisa sekali lagi merdeka.
Maryati sejenak tertegun saat gejolak pemberontakan tak lagi terasa di kedua tangannya. Lemas terkulai, Maryati menempelkan mayat Si Hitam erat ke dadanya saat ia menggendongnya keluar. Kepala Si Hitam terjuntai dari lengan gemuk Maryati, tubuhnya tergantung payah macam cucian yang terlalu lama direndam. Meski bulu-bulunya basah, hangat belum pergi seluruhnya dari tubuh kucing liar itu.
Sore itu, Si Hitam yang gugur dalam perjuangannya meraih kemerdekaan kini terbaring di atas meja kayu di belakang rumah Maryati. Di bawah pohon rambutan di mana semak serta rerumputan setinggi pinggang orang dewasa bukanlah gulma dan tak ada makhluk yang baik maupun jahat. Di samping Si Hitam, tergolek sebilah pisau dapur yang telah membelah badannya dari kerongkongan sampai anus. Kepala, ekor, serta keempat cakar miliknya telah terpisah dari tubuhnya dan dicampakkan begitu saja di bawah meja. Kulitnya kini seluruhnya lepas dari daging yang diselimutinya. Seluruh organ dalam miliknya telah dievakuasi keluar dan tertumpuk di samping tubuh kurusnya.
Siang berikutnya, saat Maryati duduk di teras menikmati teh panas serta pisang goreng kesukaannya, tak ada seekor pun kucing yang bertengger di pagar makam depan rumahnya. Sepi. Begitu sepi meski terus terdengar deru mesin dari ratusan kendaraan lalu lalang memenuhi jalan tol serta pusat bisnis yang mengepung kampung kumuh Maryati.
Materi biotik mengitari mulut mekar matahari, mengencangkan permukaan bumi menjadi kompos dan batuan. Para martir terbaring telungkup dengan lengan terentang, memberi makan rambut mereka dan membiarkannya tumbuh meliar sebagaimana sulur mencicipi udara. Bisikan astropsikis, bakteri bercahaya nekroelektrik, berlipat ganda dengan menelan planet mati. Merangkak merambati batang leher tuhan dan mengubah tubuh menjadi bara. Mata dan mulut bercahaya, sulur melilit lapisan mineral di dalam kerak bumi dan menyeretnya ke permukaan tanah. Gerinda, transmisi melintasi ruang angkasa, erat terbentang di atas hamparan teritip inti bumi.