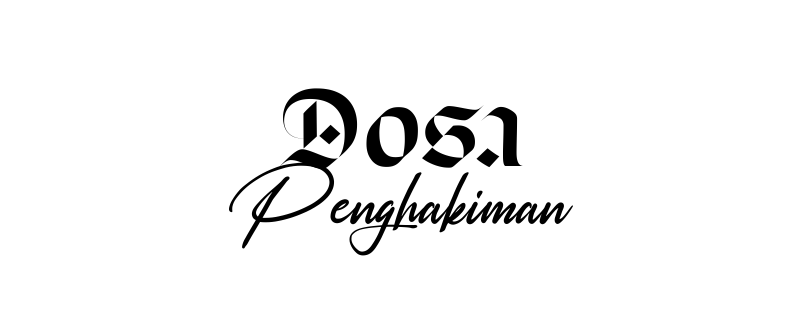
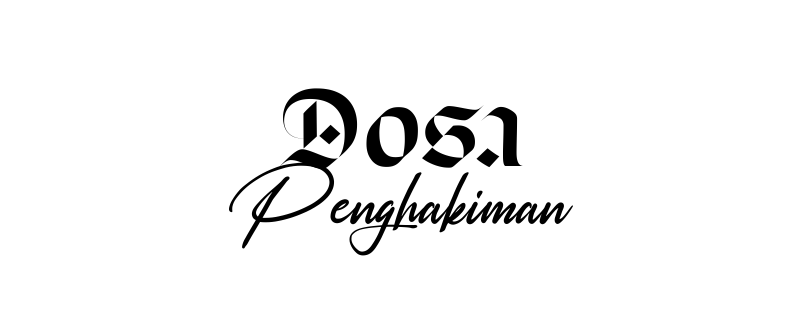
“Di tempat itu cacing dan belatungnya tidak akan mati, apinya pun takkan pernah padam terpuaskan.” — Markus 9:46
Seorang lelaki berdiri membungkuk memegangi perutnya yang berdarah, menatap nanar ke arah seorang perempuan yang membalas tatapannya dengan sepasang bola mata hijau, begitu indah, tenang tak berkedip memayat. Perempuan itu terduduk di atas jalanan basah, badannya tersandar pada dinding bangunan tua yang menggenapi sebuah lorong sempit bersama pagar panjang menjulang tinggi. Tangan kirinya mendekap sebuah tas kulit dengan sebuah lubang menganga bekas ditembus peluru, meninggalkan kosong yang menjadi jalan bagi cahaya lampu menuju tangan kurus perempuan itu yang menggenggam sebuah revolver berplat nikel mengkilap. Darah masih mengalir perlahan dari beberapa luka tusuk di sekujur badan serta sebuah luka sayat melintasi leher perempuan itu, menyisakan sedikit sekali bukti autentik bagi gaun terkoyak yang ia kenakan atas klaim bahwa ia sebelumnya putih. Wajah lelaki di hadapannya berkerut-kerut saat tembakan mematikan itu menembus saluran aliran hidupnya, mengalir deras di antara jemarinya menuju jalanan beton. Lelaki itu menyandarkan kepalanya pada sebuah tong sampah penuh karat yang seharusnya menjadi rekan untuk menyembunyikan syahwat jahatnya dari pandangan pejalan; kini menjadi bantal besi yang akan menemani keberangkatannya menuju kebebasan.
* * *
Lelaki itu mematung di ujung lorong, menyenderkan kepalanya pada sebuah pintu kayu. Wajahnya kaku dalam rasa sakit, lelaki itu masih memegangi perutnya sementara napas terus memburu mengejarnya. Napasnya kian berat melambat, ia mencoba mengimbanginya dengan berusaha menghirup sebanyak mungkin udara, mengulangi prosesnya beberapa kali sampai wajahnya perlahan terbebas dari kekangan derita. Ia menatap uap yang bermunculan dari sekujur tubuhnya, terhembus dari lubang hidung dan mulutnya. Pemandangan itu sejenak mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, ia pun mendongakkan kepalanya dan menerawang jauh ke atas, mencoba menikmati setiap kejap yang tak disertai rasa perih.
Dengan tangan kanan berlumuran darah, ia mulai meraba-raba sisi kiri perutnya, jemarinya berusaha menemukan luka yang sampai kini tak bisa lagi ia temukan. Susah payah ia mencoba menegakkan badannya dan melihat ke sekelilingnya saat hembusan napasnya semakin terlihat jelas. Dengan kedua tangannya ia mendekap tubuhnya, mencoba melindunginya dari dingin yang merasuk sampai ke tulang. Seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat, badannya seketika berdiri tegak melepaskan seluruh napas yang ada dalam dadanya bersama lenguh kesakitan sebelum akhirnya terjerembab terbungkuk memuntahkan darah, memuntahkan merah yang memenuhi telapak tangannya dan bercucuran ke permukaan beton sedingin es. Ia terus muntah berulang kali, memaksanya terhuyung ke depan menghindari genangan yang ia ciptakan. Saat kesemuanya mereda, ia kembali mencoba berdiri perlahan dan bertahan semampunya dari udara dingin, mendekap tubuhnya sekuat ia bisa sembari mengusap-usapkan kedua tangannya yang berlumuran darah pada bahu kiri dan dan kanannya.
Ia masih merasakan keberadaan perempuan itu di sana, perempuan cantik yang menjadi dosa terakhirnya. Ia menatap perempuan itu dengan rasa takut yang dapat mengguncang tubuh yang menggigil kedinginan dengan kengerian, gemetar menggigil bertumpukan mengguncang paru-parunya, memutus napas pendeknya dalam barisan tak berirama. Di tengah teror yang ia rasakan, ia terus menatap perempuan itu dengan kebencian yang seketika meracuni udara di sekelilingnya sementara rasa jijik semakin kencang melilit perutnya dengan simpul memuakkan.
Ia berbalik memunggungi perempuan itu sembari memasukkan tangannya yang berlumuran darah ke dalam saku celananya meraih bungkus rokok yang telah hancur. Dengan jemari gemetaran ia mengambil satu batang Camel Lights yang tersisa dan meletakkannya di antara kedua bibirnya yang menggigil. Ia menyalakan rokok itu dengan sebuah korek berwarna oranye dari saku celana yang lain lalu menengok ke belakang ke arah perempuan itu. Bersama tawa keras yang dipenuhi keraguan, ia menggeleng-gelengkan kepalanya sembari mengetukkan abu dari ujung rokoknya, menciptakan riak pada genangan darah di tempatnya kini berdiri.
“Kamu tertawa, tetapi juga gemetar ketakukan,” kata perempuan sembari tersenyum ramah setelah tiba-tiba bangkit dari tempatnya terbaring.
“Bah, kebetulan saja malam ini dingin sekali.” Balas lelaki itu dengan seringai tersinis yang bisa ia himpun di tengah ketakukan.
“Sayang sekali, mungkin takkan ada lagi dingin yang akan kau temui.” Ucap perempuan itu dengan senyum lebih tajam yang penuh dengan ancaman.
Lelaki itu kembali menengok ke belakang ke arah sang puan, mengangguk pelan dan membuang rokoknya lalu menenggelamkan baranya dalam genangan darah dengan kaki kirinya. Perempuan itu berjalan mendekat dan ia pun tertunduk tolol dalam kepasrahan sebelum akhirnya menggigil tak terkendali oleh sensasi mengerikan yang menyesakkan dadanya. Perempuan itu menatapnya dengan mata putih bersih serupa susu, terus mendongakkan dan menundukkan kepalanya dalam gerakan yang begitu aneh, kedua tangannya terentang ke samping, kaku dan sama sekali tak natural seolah digerakkan oleh kehendak ilahiah yang mengambil alih kefanaan cangkang kosong yang tengah ditempatinya
“Tak mampukah engkau menghadapi dosamu sendiri?” Ucap perempuan itu, menantangnya untuk mendongakkan kepalanya.
Dengan patuh ia membawa pandangannya ke atas menuju kedua mata perempuan itu, seketika leher perempuan itu terkoyak terbuka kian lebar dan mengucurkan darah memenuhi gaun putih yang ia kenakan. Lelaki itu sejenak tergagap dan kembali menundukkan kepalanya.
Perempuan itu menggerakkan kedua tangannya menuju luka di lehernya, menangkupkan keduanya di bawah pancuran darah sampai meluap dipenuhi merah yang menghitam. Ia mengarahkan kedua tangannya yang masih tertangkup ke depan kepala lelaki itu, mempersembahkan warna pengorbanan kepada lelaki yang mengakhiri riwatnya. “Silakan, bila haus darahmu belum terpuaskan, ayo Antonio, silakan.”
Tak ada jawaban. Perempuan itu pun meraih kedua tangan Antonio yang masih merah berlumuran darah dan mengurapinya dengan merah dari tangannya. Antonio pun terisak merespon sentuhan lembut perempuan itu, kengerian semakin menggelegak memenuhi kepalanya saat ia merasakan genangan darah di bawah kakinya perlahan menghangat hingga akhirnya bergolak mendidih di sekeliling sepatunya. Napasnya berat, tak kuasa menghadapi rasa hangat yang melelehkan dingin dalam tubuhnya sebelum akhirnya terasa perih menyengat menggigit kulitnya.
“Apa yang harus aku lakukan untukmu Antonio?” Ucap perempuan itu dengan nada penuh rayuan.
Ia tertunduk semakin dalam dan terus menangis terisak tak terkendali.
“Hah?” Ucap perempuan itu lebih keras, menuntut respon dari lelaki yang ada di hadapannya dan membuatnya sejenak terhenyak terdiam, tetapi sesaat kemudian tangisan Antonio kembali pecah semakin tak terkendali layaknya bocah yang sedang memperoleh hukuman.
“Apa yang harus aku lakukan, Antonio? Apa yang harus aku lakukan pada gelap yang menolak terang cahayaku?”
Perempuan itu menatapnya dengan tatapan membekukan jiwa, dengan tatapan yang disesaki kesabaran keabadian, kembali menggerak-gerakkan kepalanya secara sureal dan tak manusiawi sementara luka di lehernya terus mengucur mengeluarkan realisme kematian.
“Apa yang harus aku lakukan?” Ucap perempuan itu lagi sebelum mulai berjalan mengelilingi Antonio. ”Apa…yang… harus…aku… lakukan?” Perempuan itu kembali mengulanginya berulang kali, setengah berbisik mengikuti irama langkah kakinya mengitari Antonio.
“Mungkin yang maha bisu bisa menjawab panggilanku saat aku membutuhkannya,” ucap Antonio perlahan penuh kepatuhan bersama amarah yang teredam oleh isak tangis dan lolongan.
Perempuan itu berhenti, masih menatap Antonio yang menggeretakkan giginya dan mencoba mengendalikan rasa takut yang menyelimuti jiwanya.
“Atau kau bisa tetap menjadi pencipta suci tanpa dosa—kuasa yang membiarkan takdir busuk kejatuhanmu ini terjadi.” Ucapnya lebih lantang, akhirnya berani membalas tatapan perempuan itu dengan penuh keyakinan.
Antonio menjerit kesakitan dan terjatuh menuju genangan mendidih, menuju beton penuh darah yang seketika membakar kedua lutut dalam siksa penyesalan. Pandangannya terseret ke arah lengan kirinya, menggeretakkan giginya sekuat mungkin saat belasan cacing biru bergerak melata mencari jalan keluar dari bawah kulitnya
“Mereka hanya makan dalam kegelapan, Antonioku, mereka takkan bisa bersantap di bawah cahaya.” Ujar perempuan itu pelan, tertunduk memandangi Antonio.
“Mungkin memang sebaiknya aku tak perlu tahu akan keberadaanmu!” Teriak Antonio mendongakkan kepalanya, menggigil gemetar menahan rasa sakit, “Aku telah memberimu kesempatan berulang kali, setidaknya kau bisa tinggalkan aku saja, biarkan aku terbakar seperti biasanya, oleh kedua tanganku sendiri!” Lanjut Antonio sembari menunjukkan tekstur kasar bekas luka bakar yang ia kenakan sendiri menghiasi bagian bawah lengan kanannya.
“Mungkin saja cacing-cacing itu akan menelan seluruh kebencianmu dan akhirnya kau panggil lagi namaku demi pengampunan.”
“Tapi akankah kau jawab panggilanku, tak seperti dulu? Ataukah kau hanya akan diam dan menjatuhkan penghakiman atas apa yang kau tentukan sendiri?
“Oh, Antonio,” ucap perempuan itu lembut sambil menggelengkan kepalanya.
“Mungkin bawalah saja pesta gila ini ke dalam api kesedihanmu yang abadi.” Ucap Antonio menangis penuh kemarahan.
Perempuan itu memandang ke bawah ke Arah Antonio dengan tatapan iba. “Hebat sekali, keberanianmu ini, Antonio, akulah yang memberikannya padamu.” Ucapnya dengan lembut.
“Tapi kau memberikanku lebih dari itu,” ucap Antonio di tengah erangan kesakitan saat seekor cacing besar menembus keluar dari dalam pergelangan tangannya.
“Genggamlah tanganku Antonio, raih tanganku untuk menjinakkan santap buas dalam tubuhmu.” Jawab perempuan itu, berlutut dan membuat kolam didih di bawahnya terbelah sembari mengulurkan tangannya yang penuh darah.”
“Ambil saja tubuhku, ambil seluruh jiwaku, semuanya ditakdirkan untuk perjamuan busukmu.“ Kata Antonio, mendongak bercucuran air mata, dengan suara pelan seorang anak manusia yang telah hancur tanpa sisa. Segala sesuatu di sekeliling mereka mulai menyala dalam bara api yang mendidihkan keringat, darah, serta air mata menjadi gejolak dan uap kepedihan.
“Ayo Antonio, raihlah tanganku dan bara abadi ini seketika akan padam.”
“Habiskan sakitku, telan semuanya sampai tak tersisa lagi gelap yang menjadi makanan mereka!”
“Mari sudahi semuanya Antonio, mari selesesaikan hidupmu dalam cahaya.”
“Tapi aku tercipta untuk malam ini, inilah takdirku di dalam kegelapan malam.”
“Genggam tanganku Antonio, genggam dan biarkan dosa-dosamu mencecap cahaya.”
* * *
Seorang pria tua terbangun dari tempat tidur, terbungkus selimut bermandikan keringat yang menghalangi perjuangannya untuk melarikan diri dan memaksanya bergulat dengan kepanikan. Ia berjalan melintasi sel penjara kecilnya menuju wastafel dan memercikkan air dingin ke wajahnya yang keriput, menatap keberadaan menyedihkannya sendiri pada cermin kecil di hadapannya. Ia memegangi bekas luka di perut kirinya sebelum terduduk di toilet dan mulai menangis. Dengan tangan kanannya, narapidana tua itu menggenggam salib kayu kecil yang menggantung di dadanya dan mencoba merasakan kembali raut-raut keimanan dengan jemarinya.
* * *
Ia terbaring di atas ranjang rumah sakit yang sepertinya memang dirancang khusus untuk transfer kematian alih-alih kenyamanan kehidupan. Seorang perawat menyeka lengan kirinya dengan agen pati rasa sebelum menusukkan jarum ke dalam pembuluh darahnya dengan akurasi seorang pembunuh berkerah putih yang penuh pengalaman. Di sudut ruangan, berdiri seorang mantri dengan jas putih panjang di samping sebuah jam kayu besar dengan tatapan dingin penuh kesabaran kejam yang memaksa sang terhukum tenggelam dalam penantian akan datangnya keniscayaan maut dalam beberapa menit ke depan. Pria tua itu menerawang ke arah cermin besar di sisi kanannya, membayangkan sepasang ayah dan ibu yang bepelukan erat saling menghibur satu sama lain dalam kepedihan, menyaksikan pembunuh yang mengakhiri nyawa anak mereka akhirnya akan membayar lunas kejahatan yang ia lakukan.
Si pembunuh memandangi para penjaga ruangan satu persatu, memperhatikan senyum yang terus terpasang pada wajah mereka sebelum akhirnya pria itu berpaling dan mulai menitikkan air mata.
Seorang pendeta muda yang berdiri di sisi kanannya meraih tangannya, “Antonio, masih ingat ayat-ayat yang paling sering kamu baca, ayat-ayat yang paling kamu suka? Ayo Antonio, demi keimanan.”
Ia mengangguk pelan sementara air mata turun melintasi pelipisnya menuju kedua telinganya.
“Biarkan firmannya membimbingmu menuju cahaya,” lanjut pendeta itu, menggenggam tangan tuanya lebih erat.
Antonio menggelengkan kepalanya ragu.
“Dalam dia, kita memperoleh penebusan melalui darahnya,” ucap pendeta itu dengan nada menyejukkan.
Antonio sejenak bimbang memandangi bola mata biru gelap milik pendeta muda itu.
“Ingat lagi Antonio, ingat keimanan,” lanjut sang pendeta.
“Dalam dia, kita memperoleh penebusan melalui darahnya,” ucap pendeta itu tersenyum menyaksikan mulut Antonio mulai bergerak mengikutinya.
“Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia setia menepati janjinya dan berlaku adil, ia pasti mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” Antonio mengucapkannya bersama sang pendeta, nada beratnya kini menenggelamkan suara sang pendeta.
“Segala dosa dan kejahatan mereka, aku takkan mengingatnya lagi.” Lanjut Antonio sedirian dan sang pendeta mengangguk memberikan dukungan.
Mantri yang berdiri di sudut ruangan pun menganggukkan kepalanya, berjalan mendekat dan mengosongkan cairan putih dalam alat suntik besar yang ia pegang, mengirimkannya berputar-putar mengikuti selang infus menuju pembuluh darah sang narapidana.
“Dalam dia, kita memperoleh penebusan melalui darahnya.” Ucap Antonio kembali, tak melepaskan pandangannya dari kedua bola mata biru sang pendeta.
“Jika kita mengakui dosa-dosa kita,” lanjut Antonio terengah saat tatapan maut mulai menggantikan bulatan biru yang sedari tadi ia saksikan. “Maka ia setia menepati janjinya dan berlaku adil,” ucapnya dengan seluruh kekuatannya yang tersisa.
“Ia pasti mengampuni segala dosa kita… dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” Sang pendeta menggenapinya untuk Antonio sembari mengusap air mata dari pipi keriputnya, menutup tatapan kosong Antonio dan mulai berdoa untuk dirinya sendiri.