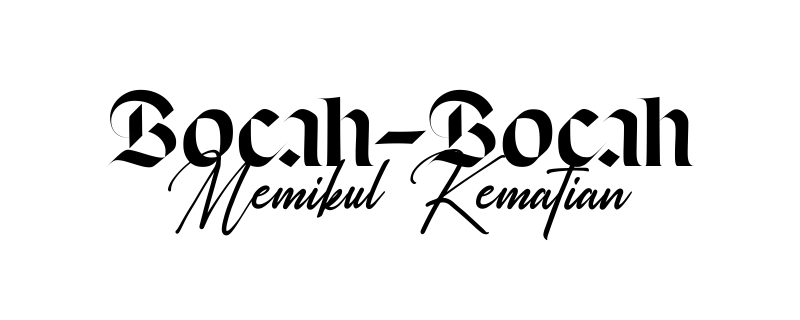
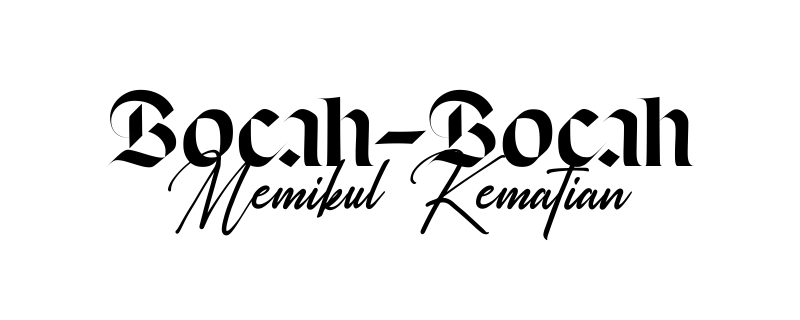
Menara gereja tinggi menjulang melampaui kabut. Segala hal lain yang pernah diingatnya kini hilang, jalanan rusak, gedung-gedung sebagian besarnya roboh atau terbengkalai mangkrak. Hanya gereja itu yang tersisa, tampak begitu jauh dan muram seperti sedia kala. Hal-hal yang dekat selalu berubah digantikan hal baru. Hal-hal yang jauh, meskipun tua, semua selalu sama.
Dia ingin bisa keluar keluar dari tubuhnya sendiri, lepas dari rasa jijik dan mimpi buruk, lepas dari lengkingan statis yang menyiksa kepalanya terus menerus. Untuk apa sebuah eksistensi bila pertobatannya takkan pernah diterima? Ia pun kembali pada dirinya sendiri sebagai orang yang dihantui mimpi buruk tentang perjalanan menuju cahaya, kepalanya dipenuhi suara-suara asing yang terus menyerukan bahwa kenyataan di sekelilingnya adalah kengerian itu sendiri, kengerian yang takkan pernah bisa ia hindari.
* * *
Gadis itu mengguncang lonceng kuningan yang menggantung jauh di atas kepalanya, mengumandangkan panggilan terakhir serupa binatang melengking. Pikiran lelaki itu seketika kacau, terendam dalam ampas asap hitam pekat. Lampu-lampu minyak berkedut bergoyang mengikuti angin, kepulan asap rokok membututi langit-langit penuh noda.
Sekelompok pria tua dengan pakaian coklat penuh noda berlarian melewati pintu keluar, langkah mereka terkunci kidung pujian. Ia memperhatikan gadis itu, menyimak dentang yang dibunyikannya, mengingatkannya pada istrinya yang pertama. Gadis itu tampak begitu anggun dalam sweter putih dan syal hitam gelap, rambutnya dipotong pendek seperti anak laki-laki. Ia sangat menyukai penampilannya. Ia sangat menyukai senyuman manisnya. Ia mengatakan semua itu saat ia datang untuk mengantar pesanannya, membawa kertas tagihan penuh keringat ke arahnya, dan menanyakan apakah ia tak keberatan menemaninya berkendara petang itu.
Gadis itu menemuinya di lorong belakang gereja, keberadaannya nyaris lenyap dalam sepatu bot dan jas panjang berwarna coklat. Lelaki kita membuka pintu belakang untuk gadis itu, tetapi dengan cerdik ia berputar mengelilingi bagian depan mobil menyusuri kontur kap dengan jemarinya yang mungil.
“Gagah sekali, jahanam.” Rahang gadis itu terkatup rapat memperdengarkan suara gemeretakan giginya.
"Lincoln Continental Mark III," ujar sang lelaki memperhatikan gadisnya berdiri di hadapan sorot lampu depan. Memperhatikan kulitnya yang mulus merona merah muda.
“Aku tahu. Adik lelakiku sering bercerita tentang mobil-mobil tua kepadaku. Ia bahkan mengatakan padaku kalau mereka menamai seri ini seperti aku.”
* * *
Ia menuntun mesin tuanya menyusuri jalanan di batas perkampungan serupa hewan pemangsa yang lesu, menukik merambati malam, turun dari persneling ketiga menuju dua menjelang tikungan tajam menyeramkan. Baris bangunan kecil kecokelatan bergelombang menyembul di bawah sorot cahaya sebelum menghilang dari pandangan, cahaya penuh debu dan garis-garis merah menyimpan kesan kenangan yang berkabut. Ia mencekik kemudinya, mencekik mesinnya sampai menderu, tembok-tembok batu yang rendah di kota itu melengkung memberi jalan pada bentuk-bentuk angker pepohonan, pagar kayu yang dijahit dengan tanah pertanian yang mengantuk di penghujung petang. Ia merasakan tangan lemas gemulai gadis itu di atas pahanya, naik meraba perut dan dadanya.
"Kau tak berasal dari daerah sini, terdengar dari aksenmu itu." Ujar lelaki itu menatap bola mata hijau gadis itu di kaca spionnya, menabrakkan mobilnya pada jalanan lurus dan menjatuhkannya menuju posisi keempat.
* * *
Lelaki itu menyimpan sebotol Schnapps dalam dasbornya untuk momen-momen seperti ini, sesuatu yang manis dan menurutnya cocok bagi perempuan mana pun, sesuatu yang disukai istrinya saat masih muda. Ia meminumnya bergantian dengan gadis itu. Ketika gadis itu sudah merasa cukup, tanpa basa-basi ia menaikkan rok miliknya lalu naik ke atas pangkuan lelakinya. Lelaki itu membuka sabuk yang kenakan sementara gadis itu melepas celana dalamnya dalam manuver yang tak manusiawi. Gadis itu menggerakkan lidahnya menelusuri telapak tangan dan jemari lelakinya.
Dalam mobilnya yang sempit itu, ia terus memikirkan mantan istrinya, mengingat kembali apa yang tersisa dalam benaknya, wajahnya, memilih aroma Schnapps yang memenuhi mobilnya sebagai napas nostalgia. Napas dari sesuatu yang tak bisa ia ingat lagi, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bahkan bukan dari ingatannya sendiri, atau mungkin sesuatu yang terkubur dalam ingatannya.
Saat semuanya usai, gadis itu melepaskan dekapannya dan berguling menuju kursi belakang, sedikit menganggkat pinggulnya dan menaikkan kembali celana dalam miliknya. Ia merapikan rok yang ia kenakan di atas pahanya dan menyalakan sebatang rokok, menatap kosong keluar jendela.
* * *
Warna-warna gelap mengabur menghangat berganti biru kekuningan menghias cakrawala. Ia menggerakkan radio, menyusuri potongan lagu-lagu pop, puing-puing statis, dan suara-suara keras melengking. Gadis itu menghabiskan Schnapss yang tersisa tanpa menawari lelakinya. Ia mengajak lelaki itu untuk melanjutkan berputar-putar, entah gadis itu sudah mabuk, bosan, ataupun telalu bodoh untuk menemukan ide lain yang lebih menarik.
Udara segar beraroma lumpur dan lautan, kabut bergulung menuruni lembab penuh logam. Seisi dunia melakukan usaha terbaik mereka untuk menenggelamkan diri dalam kelabu, menyembunyikan diri dari pandangan mata. Tak lama kemudian mereka mencapai tanah lapang, dari sana tampak empat cerobong asap yang terpisah agak jauh dari satu sama lain, dipisahkan beton datar dengan retakan rumit penuh rumput liar yang membandel kecokelatan.
“Aku tumbuh besar di kota sebelah.” Kata gadis itu membuka percakapan.
“Aku sering mencengar cerita tentang tempat itu, bagaimana suasananya dulu, bagaiana anak-anak dibuang oleh ibu mereka menjelang pagi buta, mereka menghancurkan kota itu setelah mereka menemukan mayat mereka, menemukan buntalan tulang belulang mereka.”
Saat kabar itu ramai dibicarakan, sang lelaki sibuk mengikuti laju kehidupan perkotaan, memenuhi kesehariannya dengan segala urusan kehidupan, menikah, bergaul, memesan makan siang tanpa menengok isi buku menu, selalu sajian serupa dengan meja di sebelahnya. Akan tetapi, tak lama kemudian datanglah kabar itu, terdengar di seluruh siaran radio, tercetak besar di semua surat kabar membawa kengerian. Kuburan massal di selokan Chiesa Della Misericordia, belulang tiga puluh bocah dari panti asuhan yang teronggok di sana.
Tangannya gemetar, sekujur badannya menggigil begitu keras pagi itu sampai kopi yang pesannya tumpah mengguyur surat kabar yang sedang ia baca.
Gadis itu membungkukkan badannya mendekat, memperhatikan wajahnya seolah mempelejari rahasia yang tersembunyi dalam kerut-kerutnya. “Ada apa?” Katanya. “Mereka semua adalah anak-anak setan.” Lanjut gadis itu, mengempaskan badannya ke kursi hingga kaki bersepatu botnya terangkat ke atas. “Untuk apa kau membawaku ke sini? Menuju tempat yang aku pun tak tahu di mana.” Ucapnya sembari keluar dari mobil itu, menendangkan kaki kanannya ke udara, roknya terangkat dan jatuh menampakkan pahanya yang pucat. Ia merapikan rambutnya, berputar dan merentangkan kedua tangannya dimabuk udara.
Pria itu berjalan mendekat dan mengarahkan tangannya menuju salah satu cerobong asap yang terdekat. Sisa-sisa kerapuhan tersapu dan begitu mudah terlupakan, tegak dalam kerentanan di antara ngengat-ngengat beterbangan, sayap-sayap mereka nyaris tak terlihat di atas permukaan batu-bata memucat.
* * *
Dua baris pepohonan berjajar rapi, cabang dan rantingnya dilucuti hawa dingin, berbaris menuju pintu masuk katedral. Sebuah lambang heraldik tergantung dalam ukiran batu di atas pintu kayu. Ia mencoba, tetapi pintu itu terkunci rapat. Ia pun duduk di atas tangga dan mengingat kembali anak-anak yang mengejek dan mengajaknya bermain, lagu-lagu yang mereka nyanyikan mengajaknya kembali. Ia ingat bagaimana ia memukuli mereka hingga mulut mereka berdarah. Deret gigi-gigi kecil yang remuk dan berubah warna oleh buku-buku jemarinya yang berdenyut keras. Ia mengingat kembali bagaimana ia mengikuti langkah para suster saat mereka berbaris di jalan setapak itu, seperti sebuah ritual dalam mimpi buruk, kembali menuju Chiesa Della Misericordia.
Ia adalah salah satu yang paling beruntung, cukup kuat dan cerdas untuk mengambil segala yang ia butuhkan dari mereka yang lebih lemah darinya. Dia belajar untuk membenci cara mereka membuatnya merasakan sesuatu, mempelajari kebenaran untuk keluar dari harapan. Dia sudah menelan segala sesuatu yang ia miliki, ia menyukai rasanya, ia tumbuh besar melebihi darah dan daging lemah tanpa daya.
Seorang pendeta berdiri di sampingnya, sedikit membungkuk dengan tangan di kedua lututnya. Ekspresi wajahnya menampakkan perhatian yang tulus dan mendalam. Pendeta itu masih muda, tampan, dan rambutnya tersisir sangat rapi. Di balik bahu pendeta itu ia enggan menyaksikan matahari terbit. Cahaya putih membelah panas melalui tempurung kepalanya, mentah, bersama ledakan mengerikan dimabuk penjagalan.
“Halo?” Tanya pendeta itu, meletakkan tangan kanannya di bahu lelaki itu. “Misa akan segera dimulai. Kamu bisa masuk dan duduk di dalam ataupun beristirahat di sana, tetapi mohon maaf, mohon jangan tidur di sini.”
* * *
Sebongkah batu besar teronggok di atas kap mobilnya. Kaca depannya berselaput retakan besar, yang tersisa dari kaca-kaca jendela samping kemudinya hanyalah pecahan kaca di permukaan jok kulitnya. Buru-buru ia menyapu bersih semuanya dengan tangannya, mengeluarkannya tanpa peduli perih yang dirasakannya.
Ia mengemudikan mobilnya lambat, tanpa radio, membungkukkan badannya ke depan. Aroma alkohol kental tercium dari dari sekujur badannya. Kini ia menjadi racun, bentuk-bentuk di sekelilingnya membengkok terendam asam, berubah menjadi beraneka keanehan mengerikan. Di sepanjang pemandangan yang tampak begitu familiar baginya itu, ia berpapasan dengan rombongan sebuah keluarga yang berjalan beriringan menuju kebaktian Minggu pagi. Kepala keluarga mereka berjalan paling depan, disusul istri dan ketiga anak-anak mereka.
Meski ia tak sepenuhnya yakin dengan apa yang dilihitnya, ia menyaksikan gadis yang menghabiskan waktu dengannya tadi malam di antara mereka, ia ingat betul wajah manisnya, ia berada di sana, jauh lebih muda dari sebelumnya. Ia mencoba mengkhianati perasaannya sendiri, mengecil dalam spion miliknya sebelum akhirnya hilang seluruhnya, tersesat setelah sebuah belokan, lalu belokan lain, dan belasan lainnya. Saat ia sudah berkendara cukup jauh dari segalanya, ia bergegas menepikan mobilnya, menendang pintunya terbuka, membiarkannya mengeluarkan hitam pekat mengepul sampai tak ada lagi yang tersisa di sana.