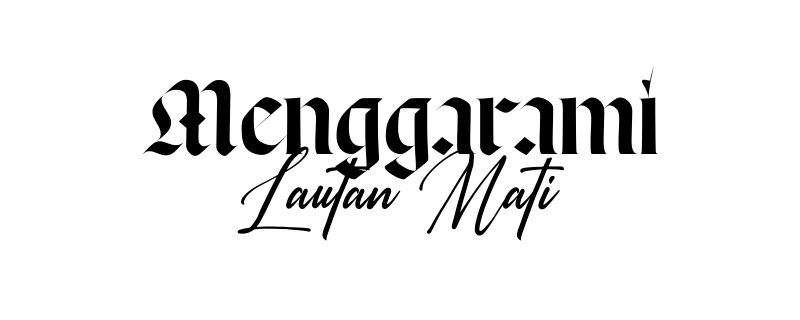
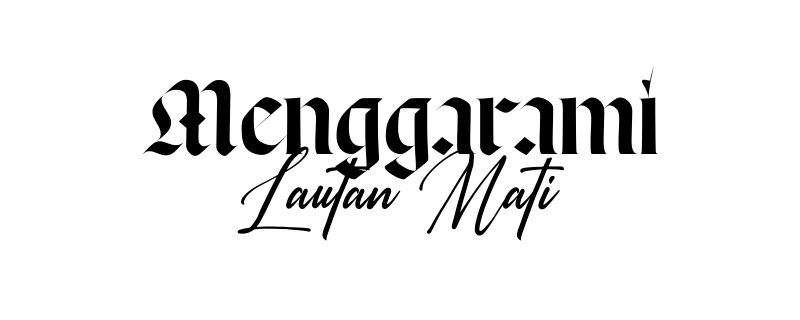
Yang penting dalamnya, bukan yang tampak dari luar apalagi sekedar penampilan, begitu kata orang-orang. Salah satu hal yang paling aku sukai adalah menggarami lintah yang berkeliaran di sekitar rumahku. Setiap pagi dan sore, aku selalu menyempatkan untuk menghabiskan waktu di teras belakang rumahku, tempat di mana mereka selalu berkumpul sepanjang tahun, sampai sekarang pun aku tak paham kenapa kenapa mereka selalu muncul bergerombol di sana. Bersama gelas kopiku, aku akan menghujankan butir-butir garam halus pada makhluk-makhluk menyedihkan itu, tersenyum kecil menyaksikan mereka mengencang mengerut hingga akhirnya mengejang begitu kencang dan tubuh mereka pun terbalik lalu lemas tanpa nyawa.
Aku selalu merasa diriku berbeda, bukan dalam artian aku ini begitu spesial tak seperti orang kebanyakan. Bayangkan seseorang yang selalu membuat dunia di sekelilingnya menjadi lebih baik, aku tak seperti itu, keberadaanku adalah kebalikannya. Rasa-rasanya aku tak ditakdirkan untuk membawa kebahagiaan, bahkan mungkin tiada tempat bagiku di dunia ini.
Ibuku ingat saat itu ia mabuk berat di sebuah klub malam bersama seorang lelaki asing, tinggi besar dengan sebuah tato naga di lengan kirinya. Yang ia ingat kemudian hanyalah terbangun di sebuah motel kecil, sekujur badan dan selangkangannya terasa sakit. Menurut polisi, lelaki itu pasti memberinya ketamin atau mungkin rohipnol. Konyol, yang ia tinggalkan hanyalah beberapa helai rambut kemaluan serta diriku.
Seharusnya saat itu ia segera mengakhiri kehamilannya sebelum membesar. Sampai sekarang aku tak mau menyalahkan ibuku karena aku tahu pasti bagaimana ia ingin sekali melakukannya. Kalau aku, pasti aku akan bergegas menuju klinik aborsi, menyiapkan satu hanger kawat untuk berjaga kalau ternyata aku terjebak kemacetan. Akan tetapi, di tempatku tumbuh besar, rasa takut akan dosa sama lazimnya dengan paranoia pada orang miskin dan gelandangan. Ibuku hanya mengusahakan yang terbaik sesuai apa yang orang-orang katakan padanya, ia melanjutkan kehamilannya dan melahirkanku, tersenyum kecil saat mendengar pujian orang-orang bahwa ia seorang perempuan yang kuat dan berani. Seorang perempuan yang patuh mengikuti perintah tuhan dan berlapang dada menerima takdir yang diserahkan kepadanya.
Bila tuhan memang benar-benar mampu mewujudkan dunia seisinya hanya dalam tujuh hari, tentu bukan hal besar baginya untuk menciptakan satu lelaki brengsek yang kemudian memperkosa ibuku. Akan tetapi, kadang aku berharap tuhan bisa lebih bijak lagi dan mempertimbangkan keputusan-keputusannya sebaik mungkin, misalnya menjadikanku seorang gadis yang mewarisi sifat baik ibuku dan bukan menurunkan kegilaan-kegilaan yang mungkin ada pada bapak haramku itu kepadaku.
Semakin aku dewasa, semakin terlihat pula kinerja genetika yang diwariskan bapakku. Di usia empat belas tahun, aku terbiasa menghabiskan malam-malamku di kamar mandi, mengangkat salah satu kakiku ke atas toilet dan masturbasi sembari membuka majalah dewasa dari era delapan puluhan. Aku sering menyelundupkan video-video porno yang kudapat dari kawan-kawanku dan meluapkan nafsuku dengannya bak seorang lelaki ingusan. Saat usiaku enam belas tahun, aku sudah memberikan felatio dalam jumlah berkali lipat lebih banyak dibandingkan gadis mana pun di sekolahku.
Aku sering nongkrong di pesta-pesta maupun klub malam, berkenalan dengan anak-anak kuliah atau altet sekolah dan menunggu mereka mengambil keuntungan dari kemolekanku. Saat itu aku termasuk bocah yang cepat belajar, saat kamu menatap mata mereka dalam-dalam dan meminta mereka untuk menidurimu malam itu juga, seketika wajah mereka akan memerah lalu tertunduk gemetar macam pecundang. Sayang sekali memang, sejak itu aku pun bersikap lebih lembut dan feminin, dengan begitu lebih banyak pula lelaki yang menghabiskan malam-malam mereka bersamaku, ironis sekali memang.
Aku bersikap macam perempuan murahan sama sekali bukan agar lelaki-lelaki menyedihkan itu mencintaiku, mau melakukan apa pun yang aku mau. Aku hanya menyukai seks, tidak lebih. Ada perbedaan besar antara melakukannya untuk menaklukkan seorang lelaki dan melakukannya karena memekmu sudah begitu basah hingga kau mulai was-was akan mati dehidrasi. Kadang aku berharap aku hanya bertemu lelaki-lelaki hidung belang, orang-orang terbanal di antara jutaan menyedihkan yang hanya memikirkan barang terkutuk yang ada di antara pangkal paha manusia. Kadang merepotkan sekali bagaimana harus bersikap dengan sebagian besar lelaki, bagaimana aku harus terlebih dahulu menjadi perempuan rendahan yang imut dan menawan hanya untuk memprogram mereka kembali, menerima kenyataan bahwa ini memang kencan pertama kami dan aku berada di atas mereka, mengisap kontol mereka.
Suatu kali ada seorang karyawan bank yang mengajakku kencan, ganteng dan lumayan tinggi. Aku sama sekali tak menyukai laki-laki pendek, bagaimana pun seksi badan mereka. Malam itu kami makan malam berdua lalu ke bioskop. Besar, berotot, dia baik, dia manis, dan dia bersikap sangat sopan. Aku tahu dari caranya memandangiku, yang ia inginkan hanya tubuhku, kebetulan sekali itulah yang aku mau. Aku benci sekali bagaimana ia harus berpura-pura menjadi bocah baik di hadapanku. Entah hanya tuhan yang tahu bagaimana brekseknya lelaki bangsat itu, entah berapa banyak perempuan sombong dan munafik yang telah ia tiduri sebelum aku.
Ada terlalu banyak perempuan yang menganggap memek mereka begitu spesial sehingga perlu ada proses penyaringan super ketat dan rumit hanya untuk memperoleh sekilas pratinjau atas kebusukan selangkangan gatal mereka. Sering aku menyaksikan bagaimana mereka melakukannya seolah mereka tak menyukai kontol sama sekali. Akan tetapi, masing-masing sajalah, sama sekali tak jadi masalah buatku toh di luar sana masih ada banyak sekali kontol yang tersedia untukku. Mungkin memang nafsuku terlalu besar hingga tak peduli lagi untuk meletakkan organ kencanku di atas pedestal.
Ah, menyaksikan bagaimana jemari karyawan bank yang besar dan tebal itu basah dilumasi segenggam popcorn mentega yang kami pesan semakin membuatku berharap ia bisa bersikap lebih bajingan. Rasanya menyesal juga tak bisa kembali ke masa-masa sekolah dahulu, saat bocah-bocah lelaki begitu tak sabaran, terus dikuasi nafsu dan ingin segera bisa ngentot bersamamu.
Aku sadar betul bagaimana hari ini kejantanan dan maskulinitas sejati telah hilang, tetapi tolonglah, aku berharap seseorang bergegas keluar dan segera melakukannya secepatnya untukku sebelum aku kehabisan cairan.
Seiring umurku, aku mulai sadar bagaimana aku kadang mengharapkan sosok kebapakan. Rasa-rasanya beruntung sekali selama ini aku tak perlu bertindak terlalu jauh karena di luar sana ada banyak sekali lelaki yang hanya berpikir bagaimana bisa ngentot. Lagi pula aku tak yakin juga apa efek valium pada ereksi, tentu tak menyenangkan sama sekali bila harus duduk di atas seorang lelaki yang kehilangan kesadaran dan mencoba memasukkan marshmallow ke dalam celengan.
Sekitar lima tahun lalu, aku mendapatkan telepon dari seorang petugas kepolisian dari kota sebelah, tentang seorang terdakwa dengan serangkaian kasus kekerasan yang mengaku memperkosa ibuku saat itu. Polisi itu mengatakan bahwa semuanya dapat dikonfirmasikan bila lelaki itu bersedia melakukan tes DNA. Benar saja, dia adalah bapak biologisku. Aku pun meminta fotonya, ternyata ia jauh lebih tua dari apa yang kubayangkan, kami berdua berbagi bola mata hitam besar berbinar yang selalu menjadi ciri khasku.
Aku pun menghadiri sidangnya di pengadilan, duduk di antara para hadirin tanpa tahu kenapa aku datang ke sana. Sepertinya aku hanya ingin menyaksikannya langsung, mendengarnya bicara dan tahu lebih banyak lagi tentangnya. Ia bukan hanya seorang pemerkosa, tetapi juga pembunuh berantai dengan belasan korban, lelaki maupun perempuan. Beberapa hari kemudian, aku baru sepenuhnya sadar bagaimana kasusnya begitu ramai dibicarakan saat itu.
Aku memperhatikannya seperti menyaksikan video porno, tanpa berkedip sedikit pun. Aku mengingat semua yang aku bisa dari rangkaian sidang yang berjalan selama hampir sebulan itu, mulai dari caranya menggaruk hidupngnya hingga bagaimana ia tampak tak nyaman dengan jas yang ia kenakan. Aku meyimak dengan hati-hati seluruh pengakuan korban, keluarga korban, serta saksi-saksi lainnya; sampai sekarang aku masih tak habis pikir bagaimana saat itu mereka semua hanya membuang waktu sia-sia. Kesombongan dingin tak acuh, senyum nakal yang begitu kasual, bahkan saat hakim menyatakan hukuman mati untuknya, tak ada sedikit pun penyesalan tergambar di wajah bapakku. Meski begitu, aku tetap berharap bagaimana ungkapan emosional para korban dan keluarganya setidaknya bisa melegakan mereka karena sepanjang proses pengadilan ia hanya tersenyum kecil saat mereka mengutuknya ke neraka.
Dari seluruh karakteristiknya yang bisa aku tangkap saat itu, sikap cuek dan ketidakpeduliannya adalah hal terbesar yang terasa begitu familiar bagiku. Saat aku masih bocah, anjing tetangga membunuh kucing kecil yang baru beberapa hari aku pelihara bersama ibuku, tepat di hadapanku. Bukannya menangis atau mengadu pada ayah tiriku, saat itu aku berjalan menuju garasi dan mengambil jeriken bensin serta korek kayu dari jaket ayah tiriku yang tergantung di dekat pintu. Aku mengguncangkan pagar kayu sampai anjing sialan itu menggonggong dan berlari ke sana ke mari tak karuan. Aku naik ke atas meja tukang kayu milik ayah tiriku yang ia letakkan di sudut pekarangan kami, membungkukkan badanku melewati pagar lalu menyiramkan bensin ke anjing itu, begitu banyak bensin sampai ia mengira semua adalah sebuah permainan. Anjing itu mendongak dan melompat-lompat berusaha menggigit aliran bensin yang aku siramkan ke padanya, memberiku cukup banyak waktu untuk memandikannya dengan bahan bakar dari kepala sampai ujung kaki. Kulemparkan jeriken kosong dan kuambi korek api dari kantung celana pendekku. Percobaan pertamaku gagal, korek mati sebelum sempat kulempar. Pada usaha kedua aku berhasil melakukannya, batang korek api yang kulempar berhasil mempertahankan nyalanya hingga menyentuh genangan bensin dan rerumputan kering pekarangan tetangga, menyulut api yang seketika menyambar anjing itu dan menjadikannya api unggun berkaki empat. Anjing itu berlali berputar-putar sembari melolong keras sebelum akhirnya melambat dan jatuh meronta-ronta di tanah.
Aku terus berdiri di sana memperhatikan binatang itu terbakar dengan senyum lebar di wajahku. Satu-satunya hal yang mengangguku saat itu adalah bau menyengat yang keluar dari tubuhnya saat terbakar. Selebihnya, aku tak ingat lagi, aku bahkan tak ingat merasa sedih kehilangan kucing peliharaanku. Kalau tak salah ingat, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu terjadi, aku merasa lega karena tak harus lagi membersihkan kotorannya serta memberinya makan.
Semenjak itu, ayah tiriku selalu mengatakan pada ibu bahwa aku adalah dajjal dengan vagina. Ibu sepertinya tak tahu lagi harus marah atau diam pura-pura tak tahu. Aku sama sekali tak bisa menyalahkan mereka, kuingat-ingat lagi, hal itu memang keterlaluan untuk ukuran bocah berumur sepuluh tahunan.
Lebih buruk lagi, sepanjang perjalanku menuju dewasa, aku tak hanya merasakan suatu kenyamanan atas kekerasan, saat pubertas menyambangiku, aku menemukan ketertarikan organik kepada semua itu, bagaimana kekerasan membuatku bergairah dan kehilangan akal sehatku.
Saat aku enam belas, aku menyaksikan bocah pendiam, gempal, dengan mata kecoklatan bernama David memukuli pacarku di tempat parkir area billiard. Pacarku yang tampan dan kekar, kapten tim basket sekolah kami, terlihat seperti sepotong roti tawar menghadapi binatang buas. Malam itu, sepulang dari rumah sakit, aku masih ingat bagaimana saat itu aku begitu bergairah. Rasanya aku ingin membenci David atas perlakuan jahatnya pada pacarku, tetapi sebenarnya aku tak bisa berhenti membayangkan kembali bagaimana tubuh gempalnya menggencet pacarku di area parkir, bagaimana ia mengunci lengan pacarku dengan lututnya dan mengujani kepala pacarku dengan pukulan-pukulan liar yang meninggalkan merah merona di kedua kepalan tangannya.
Saat aku berjalan di area parkir rumah sakit, aku teringat kembali cerita pacarku mengenai David, bagaimana perseteruan mereka hingga alamat tempat tinggalnya. Kosong, tanpa berpikir panjang aku pun bergegas pergi menuju kediamannya. Saat aku mengetuk pintu kamar kontrakannya yang lusuh, bunyi nyaring menggema memenuhi komplek sepi itu. Aku buru-buru membenarkan posisi celana dalamku yang menempel ke selangkanganku seperti kertas basah. Tak lama kemudian ia membuka pintu, hanya mengenakan sebuah celana pendek, menggenggam sekantung es batu yang ia tempelkan di buku-buku jarinya yang membengkak. Ia memandangiku lama sekali dengan tatapan jahat sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar dan membiarkanku masuk. Gemetaran menuruni sekujur punggungku saat kudengar ia menutup pintu dan menguncinya, bukan karena takut, tetapi karena fantasi seksual yang memenuhi kepalaku saat itu.
Aku tahu pasti mengenai reputasinya, bagaimana ia terkenal kasar dan berbahaya, tetapi ialah yang benar-benar kuinginkan. Kami tak mengatakan apa pun sama lain, ia tak menanyakan apa yang lakukan mengunjunginya tengah malam. Ia hanya memeluk tubuh rampingku secara kasar lalu menghempaskanku ke atas ranjangnya yang lembap oleh keringat. Ia menarik turun celana dalamku dan menggulung gaun yang aku kenakan ke atas, membuka lebar kakiku dan melahap memekkku begitu saja seolah itu sajian pertama yang ia makan seharian. Ia bercinta sebagaimana ia berkelahi, cepat dan tanpa ampunan. Ia hanya menatapku sekilas untuk memastikan kesedianku menyerahkan tubuhku ke padanya malam itu. Malam itu itu kami melakukannya dengan begitu hebat berulang kali sampai pagi. Sejak saat itu aku tak pernah bertemu dengannya lagi, sepertinya aku membuatnya ketakutan padahal aku tak menginginkan sebuah hubungan atau apa pun. Sayang sekali, David bukanlah satu-satunya lelaki hebat yang bisa memuaskanku di ranjang yang pergi meninggalkanku.
Saat kuliah, aku hamil dengan salah serang dosenku. Saat ia menawarkan aborsi, saat itu jawabanku hanya, “Oke.” Aku masih muda dan ia sudah berkeluarga, aku mungkin pantas disebut lonte, tetapi aku sama sekali tak ingin menghancurkan rumah tangga orang. Aku sama sekali tak menginginkannya untuk menikahiku, aku pun tak uang, apalagi keturunan darinya. Aku hanya menginginkan kontol super besar miliknya dan nilai A. Aku mendapatkan keduanya, tetapi kehamilan itu sama sekali bukanlah takdir untukku, semua sekedar kondom bocor dan kesialan yang mengganggu.
Klinik aborsi terdekat berjarak sekitar satu jam dari tempatku tinggal. Dengan segepok uang, aku pergi ke sana tanpa prasangka apa apun. Aku terkejut saat menemui betapa ramahnya semua orang di sana. Semua tampak bersahabat hingga aku pun bercanda menanyakan apakah akan ada diskon khusus untuk kunjungan berikutnya, saat itu tak ada yang seorang pun yang tertawa, tetapi aku tahu siapa saja yang menahan diri untuk melakukannya. Diingat-ingat lagi, saat itu memang salah satu hal buruk yang pernah aku alami. Bukan klinik dan aborsinya, melainkan rumah makan masakan cina yang kukunjungi sepulang dari sana. Entah apa yang kupikirkan saat itu, mungkin saja prosedur aborsi yang kutempuh gagal dan satu-satunya pilihan mudah yang aku punya adalah mengenyahkannya dengan sakit perut dan diare. Selebihnya, aku tidur begitu pulas malam itu. Aku membayangkan bagaimana bila aku memilih untuk melahirkan janinku saat itu, mungkin saja akan ada seorang lagi yang lebih gila dari aku.
Dosen ganteng itu tak pernah mengobrol lagi denganku, aku tak kaget, mungkin saat kamu mengatakan bagaimana dirimu tak menginginkan anak dari seorang lelaki, hal itu menimbulkan kebencian tak masuk akal pada mereka. Aku tak pernah menceritakan pertukaran kecil kami pada siapa pun dan rumah tangganya pun masih berjalan sampai saat ini. Mungkin dia kaget dengan ketidakacuhanku, tetapi itulah aku. Aku tak depresi, aku tak menangisi kejadian itu, aku tak pernah menangisi apa pun. Tidak sama sekali, bahkan saat orang tuaku mati.
Aku belum genap delapan belas saat diusir dari rumah dan kesemuanya sama sekali bukan pelajaran ataupun hukuman yang didasari cinta. Mereka hanya menyerah, terutama ibuku, ia tak tahu lagi harus bagaimana. Kejadian itu adalah usahanya untuk menyucikan diri dari kejanggalan dalam hidupnya, bukti hidup atas kekerasan dan perkosaan yang dialaminya semasa muda. Dengan kepergianku, mereka bisa fokus pada adik perempuanku, cahaya pengharapan dalam gelap keputusasaan yang menghantui rumah tangga mereka. Adikku baik dan manis, ia orang yang begitu peduli dengan sesamanya, hadir dari kesakralan maghligai pernikahan resmi di antara dua orang dewasa yang saling mencintai, sebuah resep sempurna untuk anak perempuan yang sempurna pula. Ibuku kini punya anaknya sendiri, anak yang bisa ia pandangi sepuasnya tanpa perlu teringat pada psikopat yang mengotorinya belasan tahun silam. Apes memang, bapakku menurunkan banyak sekali hal kepadaku.
Aku tak menyalahkan mereka atas apa yang mereka lakukan kepadaku. Mereka orang-orang baik yang mencintai hal-hal baik pula, wajar kalau mereka tak bisa mencintai aku. Mustahil mencintaiku dan percaya akan keberadaan neraka tanpa harus mengunjunginya. Bahwa separuh aku adalah dirinya, sepertinya bukanlah hal yang menjadi pertimbangannya saat itu, sayang sekali memang, tetapi sudahlah.
Tentu saja ada sisi terang dari segala hal, kesemuanya berarti aku terbebas dari kewajiban untuk menangis meraung-raung saat mereka meninggal. Pesawat yang mereka tumpangi saat berangkat liburan kebetulan jatuh ke laut. Peti mati di upacara pemakaman mereka kosong, seolah mereka pergi menuju liburan abadi tanpa perlu pulang lagi. Pemakaman itu mengingatkanku pada film-film fiksi ilmiah juga mitos tentang pendaratan manusia di Bulan.
Sebenarnya aku ingin bisa bertemu langsung dengan bapakku sebelum ia tiada. Ia sempat meminta fotoku dan aku pun memberikannya saat mengunjunginya di penjara. Kata mereka, bapakku terus menyimpan foto itu bahkan di pada momen terakhirnya sebelum disuntik mati, aku tak tahu merasakan hal apa saat mendengar cerita itu. Apakah pembunuh berdarah dingin itu benar-benar mencintai aku? Apakah dengan mengetahui keberadaan anak perempuannya ia memperoleh suatu kenyamanan dan menerima takdir kematiannya? Aku bahkan tak berada di samping ibuku pada momen terakhirnya, aku pun yakin ia sama sekali tak memikirkanku saat dihampiri ajalnya, mungkin setidaknya aku perlu memberikan suatu penghargaan pada bapakku mengenai foto itu.
Aku tak terlalu memahami bagaimana orang-orang sering kali menyebut hidup ini tak adil, mungkin keberadaanku merupakan sesuatu yang memang dikehendaki tuhan. Kesemuanya terasa begitu logis dan masuk akal, saat seorang baik terlahir ke dunia, ada pula seseorang lain yang melahirkan sampah masyarakat yang ditakdirkan untuk kehancuran. Kurasa orang-orang jahatlah yang membuat orang-orang baik itu benar-benar baik sebagaimana putih tampak lebih cemerlang pada latar gelap atau hitam.
Sama seperti semua orang, aku tak pernah memilih untuk dilahirkan. Entah bagaimana yang dirasakan orang, kadang aku merasa kesepian, robot tanpa perasaan di tengah kerumunan. Akan tetapi, aku tak pernah membenci diriku sendiri, aku pun tak tahu kenapa aku bebeda. Meski tak sampai depresi, tentu aku sering pula mempertanyakan semuanya. Aku kadang bertanya-tanya mengapa darah membuatku begitu bergairah. Aku bahkan lupa, atau mungkin tak pernah tahu pasti, bagaimana rasanya menangis. Apakah itu sebuah dorongan emosional tak terkendali ataukah kau bisa berhenti melakukannya saat kau mau. Apakah melegakan, menyenangka, ataukah menyakitkan? Orang sering kali bertanya apakah aku sakit atau mungkin gila. Entahlah, ibuku sering bercerita kalau sedari lahir aku hampir tak pernah menangis, hanya menatap kosong ke arahnya atau berteriak kencang dan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang.
Aku selalu mencoba terbuka dengan jawaban yang orang-orang berikan untuk pertanyaanku, aku tak marah atau dendam saat mereka menyebutku jahat dan tak berperasaan, aku menyadari hal itu, tetapi kadang semua terasa seperti usaha sia-sia orang untuk menyudutkanku atau membuatku merasa bersalah. Aku sudah mencoba terapi, berbagai macam terapi. Rasanya para terapis itu lebih tertarik untuk membedah dan mengulitiku, atau tidur denganku, dibanding berurusan dengan apa pun yang mungkin keliru dengan kondisi mentalku. Aku tak membenci mereka, hanya saja kadang semua terasa begitu tolol saat aku harus membayar uang yang tak sedikit untuk kontol-kontol bersertifikat profesi saat aku bisa mendapatkan semuanya gratis kapan pun aku mau.
Pada akhirnya aku pasrah, tak ada jawaban bagiku, tak ada seorang pun yang bisa menolongku, tak masalah. Setidaknya aku tak terlalu membahayakan orang, tak pernah sekali pun aku merencanakan untuk menyakiti orang atau membalas dendam pada siapa pun, sesuatu yang mungkin sekali banyak difantasikan orang. Mungkin aku masih beruntung, mungkin aku mewarisi bagian kecil dari kebaikan ibuku. Mungkin saja suatu saat nanti fantasi-fantasi kejam akan bermunculan dalam kepalaku, aku masih yakin takkan mengikuti semuanya kecuali dorongan itu begitu hebat sampai aku sama sekali kehilangan akal sehat. Aku sama sekali tak tertarik menghabiskan sisa hidupku di sel sempit tanpa privasi dan sesi anal bersama sipir tua yang tak pernah mencuci kontol mereka sejak perang dunia kedua. Aku pun bisa menikmati didominasi, tetapi tidak, aku lebih menginginkan kontol-kontol yang bersih terawat, setidaknya untuk saat ini.
Rasanya aku cukup puas dengan hidupku sekarang, beberapa hari lalu aku mengalami orgasme saat menyaksikan film b bersama vibrator milikku, aku pun sempat memburu dua kelinci tetangga dengan senapan anginku. Para bangsat kecil itu sering membabi buta menyerobot masuk dan merusak tanaman di kebun orang, setidaknya aku punya alasan yang dapat diterima secara sosial untuk menghabisi beberapa ekor di antara mereka.
Kalau harus jujur, untuk seorang tak berperasaan sepertiku, kesemuanya terhitung lumayan. Aku tak perlu terlalu khawatir selama aku bisa memerankan kenormalan di hadapan orang-orang. Sebagian besar tetanggaku pasti tak pernah menyangka kalau aku pernah tidur dengan anak lelaki mereka yang berprestasi di kampus, mereka bahkan sering memuji koleksi tanaman hias dan kebun sayurku.
Akan tetapi, pagi ini rasanya aku sudah terlampau lama berpura-pura, mungkin sebentar lagi aku akan gila. Selepas menjalankan rutin pagiku, ada kekecewaan besar dan rasa frustasi yang memenuhi kepalaku. Aku belum menangis, mungkin sebentar lagi. Sayang sekali, semua terjadi hanya karena aku kehabisan garam di dapurku.