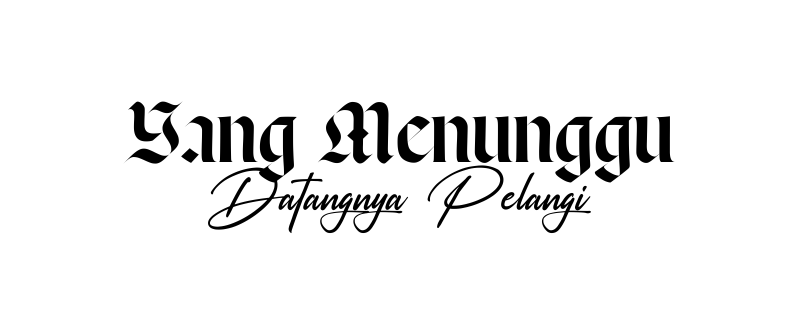
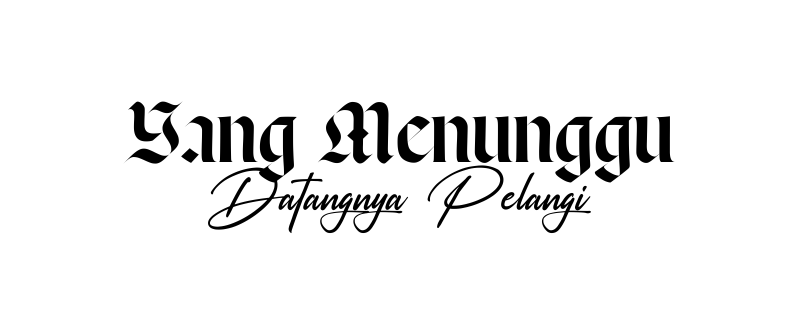
Terhitung sudah satu minggu sejak Raihan duduk di kursi belajarnya menghadap jendela yang terbuka selama dua puluh empat jam, membuat matanya tak pernah menutup menghadap luasnya langit dari munculnya matahari hingga berwarna jingga bercampur merah muda sebagai bias tenggelamnya di bagian barat. Kami belum tahu sebabnya, yang pasti ia hanya duduk sembari menatap langit. Tidak bekerja, tidak ke kamar mandi, tidak minum juga makan kecuali Ibuku yang terlalu menyayanginya harus membersihkan lantai karena air kencing dan menyuapinya agar Raihan tetap hidup, juga kadang harus memunguti fesesnya yang mengotori lantai kamar.
“Apa Ibu yakin kita tidak perlu memanggil dokter atau psikiater?” Tanyaku ketika Ibu keluar dari kamarnya membawa bekas piring dengan bubur yang masih tersisa setengah.
“Tidak Hanun, Raihan hanya menunggu pelangi. Setelah itu ia akan kembali seperti semula. Begitu katanya kepada Ibu. Pasti dan berulang kali.” Ujarnya tenang.
“Dan Ibu percaya?” Tanyaku frustasi. Hal ini sama sekali tidak masuk akal. Karena Raihan berhenti bekerja, terpaksa aku juga yang harus mengganti jatahnya untuk menghidupi kami bertiga. Seandainya Ayah masih ada, mungkin dia sudah ditampar dan ditendang hingga jatuh menggelinding sampai dasar tangga, membuat pikirannya sadar akan apa yang sudah ia lakukan. Hanya duduk tanpa melakukan apapun, di antara dirinya malas atau berlagak gila agar lepas dari tanggung jawabnya merawat Ibu kami. Jujur aku keberatan, gajiku tak sebesar dirinya yang menjadi penerjemah lisan bahasa Jepang di sebuah perusahaan internasional. Maklum, hanya akuntan biasa. Sayang berlebihan kepada Raihan membuatku malas untuk mencapai sesuatu dan membuat orang tuaku bangga, terutama Ibu kami.
Terkadang aku masuk dan duduk di sampingnya. Sebagai saudari kembarnya, aku merasa penasaran apa yang ia rasakan ketika duduk dan memandang langit sepanjang hari. Bosan, sampai aku saja mendengkur pelan. Tidak membuatnya merasa risih atau menyuruhku untuk kembali ke kamarku sendiri di sebelah.
Dua minggu kemudian aku menyerah dan hanya melakukan sebagaimana tugasku di rumah. Mungkin memang benar kata Ibu, Raihan hanya butuh untuk menunggu pelangi muncul setelah hujan di musim panas tahun ini, sesuatu yang amat sangat mustahil terjadi. Polusi kota ini cukup memberikan efek pada fenomena alam di langit yang semakin kami jarang temui.
“Aneh sekali hujan turun di musim panas.” Ujar Edi, yang baru saja masuk ke ruangan kerja dengan baju yang sedikit basah terkena air hujan. Seketika aku berdiri dan berjalan keluar ruangan sampai menemukan jendela. Benar saja, hujan deras telah turun dengan sedikit cahaya sinar matahari yang menerangi di sela-sela awan kelabu. Ada sedikit rasa lega di dadaku karena jika setelah ini muncul pelangi, Raihan akan kembali normal dan meninggalkan kursi belajarnya. Pada saat itu aku akan memukulnya dan meminta ia mengganti uang yang sudah aku keluarkan untuknya.
Aku tak sabar menunggu waktu jam pulang kerja datang. Hujan telah berhenti, awan kelabu baru setengah menyingkir, matahari muncul lagi, dan terlihat pelangi tipis membentang di kejauhan. Aku yakin Raihan juga bisa melihatnya.
Aku berlari, menaiki bus penghubung antar kecamatan dan tidak menyadari jika aku mengetuk-ngetukkan sepatuku terus ke lantai bus secara perlahan. Keluar aku dari halte, aku berlari lagi. Lelah belari dengan hak tinggi, aku melepas sepatu dan kembali berlari. Beberapa meter dari rumah, aku melihat jendela geser kamar Raihan sudah ditutup. Apa dia puas dengan hal itu? Aku harap iya. Namun, ada kesunyian aneh ketika aku sampai di rumah. Beberapa tetangga tengah memenuhi ruang tamu juga ruang tengah dalam diam.
Beberapa orang yang menyadari kedatanganku langsung memelukku seketika tanpa memberitahu apa yang tengah terjadi. Mereka menatapku dengan tatapan iba dan sedih.
“Ini ada apa ya?” Tanyaku pada Pak Rudy yang menghalangi jalanku untuk masuk ke ruang tengah.
“Seusai hujan tadi siang, kakakmu Raihan loncat dari balkon kamar atas, dan meninggal. Ibumu tadi cerita, Raihan meninggalkan catatan di atas meja belajar yang sebelumnya tak ada.”
Aku menerjang masuk ke dalam ruang tengah dimana ada Ibu dibantu tetangga yang lain membersihkan badan Raihan. Aku berlari kecil ke kamar Raihan dan menemukan catatan yang dimaksud.
“Aku kira pelangi memang simbol keindahan yang cukup pantas untuk ditunggu. Ternyata biasa saja, diriku masih terasa gelap tak tertolong.”