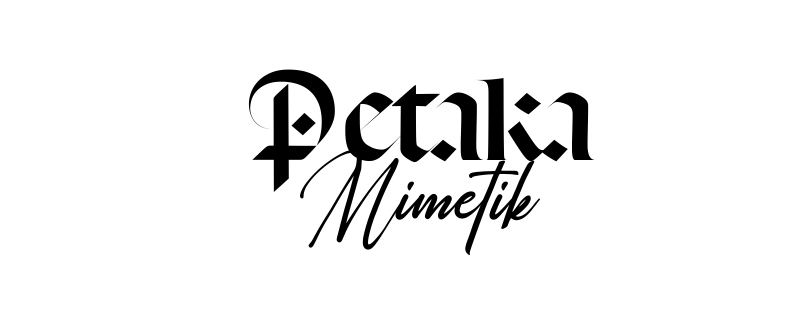
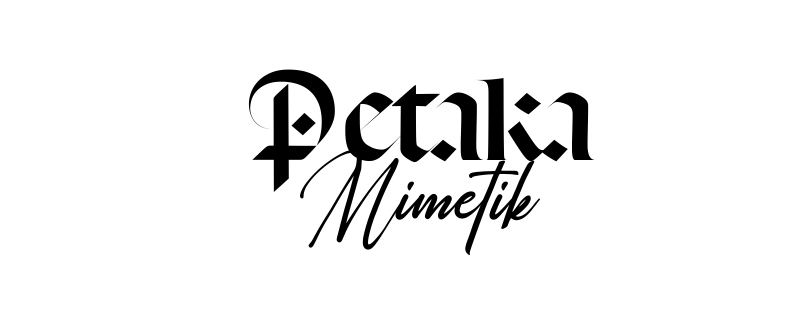
Pada era media sosial kini, salah satu pertanyaan eksistensial terbesar yang harus kita hadapi adalah apa arti menjadi relevan. Jawabannya tentu saja sederhana: terlibat aktif menjadi model/citra di antara orang-orang. Bila krisis yang kita hadapi saat ini sama persis seperti yang pernah diungkapkan Baudrillard, bahwa pertanyaan terbesar kita bukanlah kodrat dan kondisi sebuah realitas melainkan apa “nilai” dari sebuah realitas, maka seluruh pergulatan historis yang sedang kita hadapi saat ini cocok disebut sebagai kondisi pascakemanusiaan, menghilangnya referensi ontologis tradisional menuju domain pemusnahan dalam virtualitas. Kira-kira masih perlukah kita membahas kebenaran dari suatu relevansi dan apakah nilainya bagi kita?
Sejak Jacques Ellul kemudian Guy Debord pada 1967, reruntuhan politik telah tersebar berserakan di media massa, hadir kembali di hadapan kita sebagai hegemoni kekuatan spektakuler yang berperan dominan dalam politik tontonan terpadu, reifikasi kultural mahabesar di mana media lambat laun menjadi satu-satunya penentu kebenaran kita. Kehidupan yang didominasi modernitas proses produksi, hadir di tengah masyarakat sebagai akumulasi besar tontonan-tontonan. Segala yang dahulu dihidupi langsung kini sekedar menjadi representasi atau gambaran-gambaran.1 Banyak yang menyebut kondisi modern dalam ranah produksi-konsumsi tersebut sebagai kapitalisme akhir, sebuah keruntuhan paralel nilai guna menuju nilai tukar baik secara politik maupun ekonomi—saat segala macam pengalaman konkret tereduksi menjadi representasi kebenaran.
Menurut Baudrillard, tontonan terpadu yang diramalkan Debord tersebut telah digantikan oleh realitas integral—terintegrasinya segala sesuatu yang pernah dibayangkan Debord menuju media sosial. Bila masyarakat tontonan Debord menggambarkan sesuatu yang sering kita sebut sebagai pascamodern, maka kebenaran integral Baudrillard adalah gejala pascakemanusiaan, dengan bentuk politik dan ekonominya sendiri, yakni terserapnya seluruh konsepsi mengenai nilai tukar menuju simulasi total. Sebuah realitas di mana segala sesuatu dalam proses produksi dan perekonomian dapat diubah-ubah begitu saja, diputarbalikkan, dan dipertukarkan menurut spekularitas tak tentu sama persis seperti politik, mode, dan media.2
Meski kesemuanya tampak begitu nyata, tetapi tetap saja terasa tak masuk akal. Sebagai penghuni realitas integral, kita semua cenderung fundamentalis. Kita terbiasa mendukung fundamentalisme tak berdasar, fundamentalisme cair teknokrasi silikon para penggiring opini serta pemandu soraknya, fundamentalisme yang terus terurai dan berkait kembali menjadi ribuan diaspora mentaldi lusinan linimasa berbeda. Gila memang. Kita pun cenderung fanatik dalam menjalankan komitmen untuk meninggalkan sesuatu yang kita puja-puja sebagai kemanusiaan, kita sengsara karena kita memiliki segalanya tanpa pernah mengenggam apa pun, menjadi siapa saja tanpa identitas apa pun. Lantas bagaimana? Apa lagi yang bisa kita lakukan?
Bukan hanya kaum konservatif, kiri ortodoks pun cenderung paranoid terhadap apa yang mereka pahami sebagai simulasi, sebuah muslihat yang menghapus batas antara benar dan keliru, mungkin karena keberadaanya melambangkan bentuk dekaden sebuah ketidakaslian, kemerosotan total dari natural menuju integral.
Rasanya tak sepenuhnya keliru menyebut obsesi orang-orang pada Orwell serta pengawasan panoptik ala Foucauld sebagai nostalgia, proyeksi kerinduan kita pada orde baru, rasa kangen tak terbendung pada mendiang Soeharto—musuh yang mudah dikenali lalu ditumbangkan lewat berjilid-jilid reformasi dan penokohan. Kesemuanya adalah pengharapan atas kembalinya realitas “autentik” beserta segala prinsipnya. Akan tetapi, hegemoni realitas integral terbentuk dari ketiadaan otonomi yang bahkan mereduksi kesalehan materialis menjadi kesesatan metafisik paling menyedihkan. Kenyataan sendiri sebenarnya masih sama seperti sedia kala, tetapi kini tak ada lagi gunanya merefleksikan kenapa kita harus beranggapan seperti itu.3
Petaka politik yang sebenarnya terjadi saat ini adalah bagaimana kontrol telah tergantikan oleh hegemoni keterasingan, mengebiri segala macam kritik sosial dengan menafikan autentisitas referensi utamanya. Hegemoni kontemporer ini bergantung pada likuidasi simbolis atas segala nilai yang mungkin. Istilah seperti simulakrum, simulasi, dan virtual menggambarkan dengan baik proses likuidasi tersebut—di mana signifikansi segala sesuatu tereliminasi oleh tanda-tanda keberadaannya sendiri—membengkak dan berlipatnya tanda-tanda tersebut memarodikan kenyataan ideal yang sama sekali mustahil tercapai.4
Tak ada lagi yang tersisa bagi kita selain sirkulasi meme-meme dalam kecepatan yang terus terakselerasi. Lebih suram lagi, sirkulasi tersebut adalah satu-satunya perangkat yang tersisa bagi kita untuk menilai autentisitas kenyataan, termasuk kenyataan eksistensial kita, relevensi kita di jagat maya masyarakat madani.
Sebenarnya, situasi tersebut di atas sama sekali bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam riwayat manusia. Kita semata-mata lupa bahwa realitas pascakemanusiaan yang mungkin sedang kita huni saat ini telah dikonfigurasikan sebelumnya dalam kenyataan prasejarah atau mungkin prakemanusiaan.
“…hipotesis tersebut memungkinkan pemikiran logis bahwa simetri antar mitra mimesis, rintangan hidup yang muncul dari suatu model yang bertransformasi secara otomatis menjadi pesaing, mengajarkan beberapa hal pada nenek moyang kita; kemampuan untuk menyaksikan orang lain, sebuah mimesis ganda, sebagai alter ego sekaligus kapasitas yang sesuai untuk membangun salinannya dalam dirimu sendiri melalui kesadaran serta refleksi.”5
Dalam kutipan tersebut di atas, René Girard menggunakan istilah “rintangan” ataupun “perintang” dalam dua konteks yang berbeda: mediator eksternal yang berperan sebagai penghenti persaingan mimetik yang terus tereskalasi; serta versi patologis dari persaingan mimetik yang terkontaminasi oleh hasrat metafisik di mana persaingan tersebut tereskalasi menuju titik di mana subjeknya tak lagi tertarik pada apa pun selain persaingan itu sendiri.
Pada berbagai fiksi kontemporer maupun mitos dan cerita rakyat, persaingan atas hasrat mimetik yang mendorong plotnya seringkali tereskalasi menjadi sebuah konflik. Bagi Girard, arketipe dominan dalam penuturan kisah fiksi adalah bagaimana protagonis membuat model mengenai relasinya dengan liyan (salinan dari dirinya sendiri) melalui sebuah proses imitasi (persaingan mimetik) yang lambat laun terkulminasi menuju poin di mana protagonisnya berusaha menyingkirkan ataupun menggantikan posisi pesaingnya.
“Persaingan tidak muncul begitu saja akibat pertemuan tak sengaja antara dua keinginan atas objek yang sama, tetapi sebaliknya, subjek menginginkan suatu objek karena si pesaing menginginkannya (terlebih dahulu). Keinginannya tumbuh manakala pesaing menunjukkan pada subjek bagaimana objek tersebut layak untuk ia dambakan. Si pesaing kemudian berfungsi menjadi sebuah model bagi subjek, tidak hanya dalam pendapat maupun penampilan, tetapi hal yang jauh lebih signifikan, dalam hal hasrat dan keinginan.”6
Persaingan yang muncul oleh hasrat mimetik seringkali berakhir dalam skenario kejam dan mengerikan, setiap subjek yang terlibat pada akhirnya terlahir kembali menjadi kembaran-kembaran mengerikan yang menandai krisis keserupaan; saat para pesaing mengintensifkan perjuangan mimetiknya, mereka pun menjadi identik satu sama lain, memicu krisis identitas patologis yang hanya dapat diselesaikan lewat kekerasan, baik fisik, emosional, maupun simbolis.7
Lewat serangkaian asumsi antropologis, Girard membayangkan bagaimana logika pembentukan masyarakat sosial tak jauh berbeda dengan logika narasi-narasi sastrawi.8 Manakala persaingan mimetik harus dilarang karena konsekuensi-konsuekuensinya yang merugikan masyarakat, orang-orang pada akhirnya harus mengalihkan kekejaman mereka pada korban pengganti yang difungsikan sebagai objek pengalihan kekerasan, seekor kambing hitam.9 Girard menjelaskan bagaimana kemanjuran magis keberadaan kambing hitam dengan mengidentifikasi dua varian keinginan mimetik: mimesis akuisitif yang memecah belah pihak-pihak yang terlibat, yang menyebabkan dua individu atau lebih menginginkan objek yang sama persis pada waktu bersamaan; serta mimesis konfliktual yang menyatukan, mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menyepakati satu musuh serupa yang sama-sama ingin mereka hancurkan.10 Secara historis, mekanisme ritualistik dalam pemujaan maupun pengorbanan kambing hitam tersebut sebagian besarnya bekerja dalam domain religius, yang secara antropologis didasarkan pada keperantaraan korban pengganti—seseorang harus mati sehingga masyarakat dapat terhindar dari petaka yang mungkin saja timbul dari persaingan-persaingan yang tak terkendali.11
Untuk memahami budaya peradaban manusia, kita perlu memahami bagaimana pembatasan maupun pengalihan dorongan mimesis lewat tabu dan beraneka ritual pada akhirnya mampu menyebarkan serta mengabadikan efek rekonsiliatif dari keberadaan kambing hitam. Dalam konteks ini, agama-agama dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dariterulangnya konflik yang pernah muncul sebelumnya. Satu-satunyayang sakral adalah kekerasan, perdamaian dapat terjaga hanya bila para subjeknya memuja kekerasan tersebut semata-mata sebagaipembawa perdamaian, meski tentu saja prosesnya tak pernah lepas dari kekerasan sakrifisial dan ritualistik.12
Mungkin keberadaban kita adalah produk mekanisme kambing hitam Girard.13 Lain dengan yang diungkap Freud, kita tak membangun peradaban untuk mencegah pembunuhan, tetapi menciptakan kondisi spesifik untuk melangsungkan pembunuhan tertentu: pembunuhan sakrifisial yang mencegah petaka mimesis tanpa akhir, kekerasan ritualistik demi pemenangan mimesis konfliktual di atas mimesis akuisitif.
Pendapat Girard tersebut di atas bukan sepenuhnya mengenai agama, melainkan teori mengenai pertumbuhan peradaban yang dibangun lewat ritus pengorbanan manusia, atau lebih subversif lagi, lewat pengorbanan ritualistik atas manusia-manusia. Menurut Jean-Michel Oughourlian, pendapat Girard mengenai agama-agama hanyalah salah satu aspek dalam teorinya mengenai relasi mimetik manusia.
Krisis mimesis dalam masyarakat beragama terselesaikan lewat kekerasan dalam ritus pengorbanan, gagasan relijius mereka menjadikan korban sebagai kendaraan maupun sarana transformatif dari sesuatu yang sakral, mimesis itu sendiri, sesuatu yang sebenarnya tak pernah konfliktual di luar dampak persebarannya di tengah komunitas masyarakat. Pengonsentrasian mimetik pada sosok korban mengubahnya menjadi kekuatan yang mendamaikan dan membawa keberaturan, sebuah mimesis positif yang muncul dalam ritual-ritual pengorbanan.14 Akan tetapi, proses ini tak berjalan sendiri begitu saja di tengah kompleksitas komunitas manusia. Menurut Girard, kesemuanya saling bertautan dan berlipat ganda, sama seperti yang sering dituturkan dalam kisah-kisah kemanusiaan, setiap drama mengenai suatu fenomena sosial pasti melibatkan rasa iri dan kedengkian.15
Baik Georges Bataille maupun Jean-Paul Sartre, beranggapan bahwa dilema eksistensial terbesar kemanusiaan adalah ketiadaan keakuan yang sepenuhnya esensial.Manusia tak pernah sepenuhnya yakin akan apa yang semestinya ia dambakan, pada usaha terakhirnya, manusia mendambakan keberadaan, sesuatu yang sama sekali tak pernah ia milikidan tampak dimiliki oleh orang lain. Ia pun menyaksikan orang lain, meminta penjelasan tentang apa yang harus ia dambakan demi mencapai keberadaan tersebut.16 Hasrat manusia, dimensi libidinal kemanusiaan dalam eksistensi sosial, seluruhnya berada dalam mimesis abadi. Hasrat sendiri pada dasarnya mimetik, tertuju pada objek yang diinginkan oleh model kita (orang lain), menumbuhkan persaingan-persaingan, kodrat mimetik dari sebuah konflikadalah ketiadaan objek yang layak untuknya, objek yang dapat memuaskannya selamanya.17 Persaingan adalah sisi lain dari homogenisasi, terdapat potensi tak berbatas atas derita eksistensial manakala semua orang menghuni ruang universal tanpa identitas yang solid, sebuah krisis kolektif yang tumbuh dari hilangnya perbedaan antar individu, memicu bola salju kekerasan yang saling bertimbal balik dan terus tereskalasi. Keserupaan adalah pertempuran menyedihkan di mana setiap salinan terus terlibat langsung hingga momen di mana salah seorang di antara mereka membunuh salah satu yang lainnya, saat kondisi tersebut menyebar, terjadilah skenario perang semua melawan semuanya seperti yang dibayangkan Hobbes.18 Yang seluruhnya serupa sama sekali tak memiliki relevansi, mereduksi semua menuju kesengkarutan nol, sebuah kiamat virtual.
Wajar bila Girard memegang pandangan anti-sekuler yang begitu radikal bahwa agama-agama adalah pondasi utama masyarakat sosial.19 Sebagian besar karya Girard terdiri dari antropologiyang tak lazim, sebuah persilangan antara sosilogi fungsionalis Émile Durkheim serta kritik kultural Freud, khususnya Totem dan Tabu. Baginya, parameter utama yang membatasi antara modern dan pra-modern adalah keberadaan aspek yudisial, subtitusi dari aturan-aturan depersonalisasi yang menyangkal/mencegah katarsis keingininan komunitarian atas pembalasan dendam secara mandiri.
“Bila kita membandingkan masyarakat-masyarakat yang menganut suatu sistem peradilan dengan masyarakat yang mempraktikkan upacara pengorbanan, perbedaan antara keduanya adalah bagaimana kita dapat mempertimbangkan ketiadaan lembaga-lembaga (peradilan) tersebut sebagai dasar untuk membedakan masyarakat primitif dan beradab.”20
Keberlanjutan antara yang arkais dan modern dalam teori-teori Girard adalah keberadan kiasan psikonalasis Freud. Secara umum, Girard cenderung menghindari teori Freud atas dorongan/stimulus instingtual, namun menemukan utilitas lebih besar pada penerapan psikonanalisis untuk mengenali dinamika kolektif yang impersonal dalam formasi budaya. Dengan kata lain, penerjemahan metapsikologi Freud menjadi istilah-istilah referensial dalam ide Durkheim, misalnya saja, ide bahwa tujuanritus pengorbanan adalah mengembalikan harmoni dalam komunitas dan memperkuat tatanan sosial.21 Bagi Girard, kebenaran fundamental mengenai kekerasan adalah bagaimana semuanya akan tereskalasi bila tidak segera ditenangkan.
Peran pengorbanan dalam ide Girard adalah mendinginkan gejolak dengan mengarahkan kekerasan menuju saluran yang tepat. Kunci keberhasilan mekanisme sakrifisial adalah statusnya sebagai suatu ritual, yang selalu merupakan sebuah reka ulang atas peristiwa mengerikan yang sebelumnya pernah terjadi. Karena setiap ritual adalah sebuah peragaan, logika yang mendasarinya adalah mimesis. Ritual adalah sebuah representasi sekaligus pengganti dari suatu krisis. Akan tetapi, terdapat pula logika anti-representasional dalam suatu ritus pengorbanan, bahwa lewat penggantian, segala perbedaan pun lenyap dan suatu hal dapat digantikan maupun ditukar dengan hal lain.22
Dalam hal ini, dimensi ritualistik yang sangat vital dalam mekanisme sakrifisial tersebut adalah peragaan ulang atas kekerasan-kekerasan yang pernah terjadi sebelumnya, yang kemudian berhasil menyelesaikan suatu krisis sosial.
"Para pelaku ritus pengorbanan berusaha untuk memroduksi sebuah replika, semirip mungkin berikut segala detailnya, dari suatu krisis yang sebelumnya pernah terjadi dan akhirnya selesai begitu saja lewat kebulatan viktimisasi. Setiap bahaya, nyata maupun imajiner, yang mengancam suatu komunitas, diserap dalam bahaya paling mengerikan yang dapat mengancam suatu komunitas yakni krisis sakrifisial. Ritus tersebut adalah pengulangan dari pembunuhan spontan yang dapat mengembalikan keteraturan dalam komunitas, mengantikan korban jiwa dengan kambing hitam… Dalam mekanisme kambing hitam tersebut kita dapat menyaksikan metamorfosis dari kekerasan resiprokal menuju pembatasan lewat kesepakatan-kesepakatan dan kebulatan suara."23
Setiap ritual mengandung dua macam jejak, peragaan kembali suatu krisis di masa lampau serta proyeksi efek katarsis dari krisis tersebut di masa mendatang. Krisis di masa lampau yang direpresentasikan oleh penggantian mimetik dalam sebuah ritual pengorbanan adalah kekerasan kolektif. Pengorbanan menjadi suatu istilah yang dapat digunakan untuk mereferensikan fenomena kompleks kekerasan kolektif dan korban jiwa yang pernah ditimbulkannya, rasionalisasi mistikal sekaligus ritualisasinya.24 Menurut Girard, prasyarat mutlak atas keberlangsungan sejarah suatu komunitas adalah ritus pengusiran setan atas nafsu pembalasan dendam. Hal tersebut berlangsung terus menerus lewat ritual pengorbanan yang merupakan pengulangan mimetik dari fenomena kemunculan kambing hitam yang berhasil memutus siklus kekerasan retributif.
TL;DR; menurut Girard, manusia berhasil meninggalkan era jahiliyah dengan mengarahkan kekerasan dari suatu konflik mimesis, semua melawan semua, menuju korban sakrifisial yang merupakan pengganti dari korban sesungguhnya,korban yang pada akhirnya tereifikasi dan tak perlu "ada" lagi. Benarkah semua itu? Kekerasan mungkin memang bukanlah jawaban atas segala sesuatu. Akan tetapi, apakah benar bahwa kekerasan adalah salah satu pertanyaan paling kuno yang pernah dihadapi kemanusiaan, pertanyaan ya dan tidak, pilihan untuk melakukannya ataupun tidak?
Oughourlian, seorang psikoanalis yang mendedikasikan sebagian besar karirnya pada karya-karya Girard, menerjemahkan teori Girard menjadi ide mengenai psikologi interdividual, sebuah inovasi atas teori Freud yang banyak terinspirasi oleh tulisan Marcel Proust. Secara umum, Oughourlian menggambarkan bagaimana persaingan mimetik selalu berakar dari dua hal: klaim kepemilikan individual atas hasrat yang ia rasakan; serta klaim atas anteritiotas hasrat individual, senioritasnya atas hasrat yang dirasakan orang lain, hasrat orang lain yang menimbulkan dan menjadi model dari hasrat yang ia rasakan.25 Kegagalan dari kedua klaim tersebut mereduksi individu menjadi kekosongan, yang pada dasarnya, adalah kodrat keberadaan kita. Ya,kita adalah legiun kekosongan.
Salah satu hal paling krusial yang harus kita cermati adalah dimensi temporal sebuah proses mimesis. Persaingan mimetik, dalam bentuk laten maupunyang termanifestasi sepenuhnya, terjadi dalam parameter struktural psikologis manusia mengenai waktu, sesuatu yang tak dapat dibandingkan dengan waktu linier yang tak bisa diputarbalikkan begitu saja. Dalam pemahaman Oughourlian, konflik mimesis selalu mengikuti pola migrasi dari dua titik percabangan, N dan N'
“Konstitusi diri dalam waktu fisik dapat dirangkum dengan vektor linier dari masa lampau menuju masa depan. Hasrat yang dirasakan sangmodel (H) memicu lahirnya keinginan dalam diri subjek S secara mimetik (h), yang kemudian membawa subjek s (subjek S dengan kebiasaan baru berdasarkan si model) maujud menjadi kenyataan. Begitulah urutan sebenarnya bila digambarkan dalam waktu fisik, dari masa lalu menuju masa depan. Akan tetapi, urutan ini tak berlaku secara psikologis karena semua berlangsung begitu saja tanpa sepengetahuan para protagonis.”26
Pada poin N, subjek mengklaim hasrat yang ia rasakan sebagai sesuatu yang sepenuhnya miliknya sendiri, sesuatu yang tentu saja merupakan sebuah ilusi.
“Individu pada titik N, dalam kondisi paling banal dan normal, takkan bisa bertahan kecuali diyakinkan bahwa ia memang pemilik mutlak atas segala hasrat yang ia rasakan. Solusi paling sederhana baginya adalah melupakan keberbedaan dari hasrat yang ia rasakan dan meyakini bahwa kesemuanya benar-benar miliknya seorang. Pada kenyataanya, hal ini bukanlah melupakan karena melupakan sesuatu berarti pernah mengetahui hal tersebut sebelumnya, sepenuhnya.”27
Amnesia adalah kebenaran mendasar eksistensi kita. Proses melupakanlah yang selama ini terus menjaga keberlangsungan suatu individu, lupa selalu mengawali proses pembentukan keakuan. Aku yang baru selalu dapat dibangun dengan melupakan "liyan" dalam hasrat yang dirasakan seorang individu.28
Lain dengan banyolan Sartre yang begitu populer, kebebasan sama sekali bukanlah kutukan terbesar manusia, lebih apes lagi, kita dikutuk untuk terus melupakan segala sesuatu. Lupa adalah diktator yang memperbudak keberlangsungan eksistensi manusia, lupa adalah basis fenomenologis kemanusiaan, keakuan kita adalah produk dari proses melupakan yang terjadi terus menerus secara mimetik di antara individu-individu maupun dalam komunitas sosial, melupakan sesuatu yang sama sekali tak pernah sepenuhnya kita ketahui sebelumnya.
Mimesis dapat bekerja membentuk keakuan hanya bila hasrat melupakan asal muasal mimetiknya sendiri, lupa bahwa ia berasal dari imitasi atas hasrat orang lain (hasrat H) yang juga merupakan milik orang lain. Begitulah subjek smengenali dirinya sebagai subjek otonom, eksis menyerupai subjek otonom, eksis merasakan keakuan. Hal ini sejalan dengan sabda Hegel bahwa suatu hasrat selalu menegasikan hasrat liyan.29
Lebih aneh lagi, bila konsepsi autentisitas keberadaan kita sepenuhnya keliru, makakita sama sekali bukanlah diri kita sendiri. Gagasan ini membawa kita menuju gereja Santo Agustinus dan hakikat dosa asal; bahwa kita hina bukan karena kita benar-benar jahat, tetapi karena kita tak mampu menciptakan kebaikan (secara mandiri tanpa dicontohkan). Sampai poin ini, lagi-lagi logika terus mempermainkan kita tanpa henti. Relasi mimetik selalu berakhir dengan konflik mimetik pula, entah kekerasan fisik maupun simbolis. Adakah ekspresi klinis yang dapat menggambarkan hasrat mimetik? Apakah hal tersebut adalah persaingan? Apakah setiap harinya kita tak sekedar menyalin dan menirukan, tetapi terlibat langsung dalam persaingan-persaingan?
Dari Girard kita dapat berasumsi bahwa hasratbukanlah hal privat maupun personal, tetapi publik dan kolektif. Sama halnya bahasa, hasrat pun timbul dan berkembang dari keberbedaan. Konsep keakuan pada dasarnya adalah halusinasi massal mengenai keberadaan aku, halusinasi yang muncul dari hasrat kolektif atas soliditas eksistensial di antara individu. Kesemuanya adalah sebuah mimesis, terus menular, seduktif, dan plural. Sama sekali tak aneh bila hal ini selaras dengan apa yang dibayangkan Karl Marx saat menggambarkan fetisisme komoditas. Setiap subjek yang terlibat adalah model, atau lebih tepatnya, berharap untuk menjadi model penentu tren karena model tanpa imitator tentu tak layak disebut sebagai model. Serupa juragan tanpa budak, mengidentifikasi diri lewat suatu model adalah penghiburan atas kemalangan ketidakmungkinan memperoleh segala sesuatu yang dimiliki sang model, dengan demikian ia pun terjerat dalam meme untukbersikap dan berperilaku seperti model itu sendiri.30
Begitulah semua orang, dikendalikan hasrat mimetik-imitatif untuk menjadi aku yang lain, hal yang menimbulkan ketidakstabilan dalam setiap bentuk relasi sosial. Lebih lanjut, kecurigaan-kecurigaan pun turut memperkeruh relasipenuh racun dalam masyarakat, bagaimana kadang kala kita melihat para model membangun relevansi mereka di tengah masyarakat serupa vampir melalui proses alienasi semi-sukarela yang terus-menerus kita alami.
Kesadaran manusia terbentuk saat ia terpaku pada liyan dan liyan yang spesial yakni si kambing hitam, sebuah penanda transendental
Para imitator sering kali merasa cemburu pada model karena mereka memahami bagaimana peran si model adalah sesuatu yang harus dipertahankan pula dengan iri dengki dan kecemburuan. Keterkaitan konstan antar individu yang digambarkan Girard adalah sebuah reprositas asimetris di mana kesadaran subjek terbagi antara kecenderungan submisif dan amarah yang ia tujukan pada model.31 Mungkin inilah sesuatu yang biasa kita kenali sebagai kebencian, mereka yang menjadi penghalang bagi kita untuk memuaskan suatu hasrat sekaligus menginspirasi kita untuk terus mendambakan hal tersebut, adalah objek dari kebencian kita.
Inti dari psikologi interdividual tersebut adalah fenomenologi, hasratlah yang terus membawa kita menuju permukaan eksistensi aktual dengan mewujudkan sosok aku yang memikul hasrat dan keinginan.32
Salah satu fenomena besar dalam proses tersebut adalah berbagai pengalaman berbeda mengenai modalitas waktu yang tak kompatibel dengan pemahaman/kesadaran individual: disjungsi antara waktu psikologis dalam proses melupakan serta waktu fisik yang memunculkan ketidakrelevanan. Individu mengaku sebagai pemilik hasrat h pada poin N, hasrat h pada akhirnya menemukan kembali kesamaannya dengan hasrat H, keterlambataninilahyang membawanya menuju N'. Pada N', subjek mendeklarasikan anterioritas (keterlebihdahuluan) hasrat yang ia rasakan atas hasrat liyan, hasrat yang sebenarnya menjadi asal muasal keberadaannya sendiri. 33
N' adalah lahan subur bagi neurosis dan psikosis yang menurut Oughourlian merupakan fenomenamimesis lainnya; manakala hasrat h menegaskanan terioritasnya (kelebihdahuluannya) atas hasrat H, saat itu pula ia mengklaim kepemilikan atas objek yang didambakan keduanya. Penyakit mimetik ini tak melulu mengenai kekuasaan seperti yang digambarkan Nietzsche, tetapi lebih kepada keberadaan ataupun subjektivitas psikologis. Psikosis dan Neurosis terjadi karena subjek yang mendamba sama sekali bukanlah entitas nyata secara fenomenologis, subjek s terasing dalam waktu psikologisnya sendiri, waktu yang hanya eksis di alam memori, satu-satunya waktu yang benar-benar berarti dalam subjektivitas manusia, waktu yang terasa paling nyata dan sejalan dengan realitasnya.
Bila kita hendak mempercayai hipotesis mengenai hasrat mimetik tersebut, kita perlu meninggalkan keyakinan bahwa diri adalah satu-satunya sumber atas segala macam hasrat. Pergerakan hasratlah yang terus membentuk struktur dinamis suatu subjektivitas secara gradual, terus berubah dan mempertahankan diri menciptakanilusi konsistensi keakuan. Dalam penjara fenomenologis ini, subjek s harus melakukan perlawanan demi menegakkan keakuannya. Individuasi adalah proses yang berakar dari urgensi pelepasan keakuan dari dimensi asing di mana ia bermula.
Waktu psikologis berada dalam dinamika relasi mimetik yang sama sekalitak stabil, menjadikannya sesuatu yang beroperasi layaknya mistifikasi. Waktu fisik tak memiliki suatu realitas psikologis meski keberadaannya dapat diakses lewat kesadaran/kecerdasan manusia, oleh karenanya ada pula realitas kognitif, tetapi hal ini hanya dimungkinkan lewat pemahaman ataupun pertanyaan atas kebermulaan (anterioritas, pada waktu fisik) liyan, prioritasnya atas hasrat yang kita rasakan, dan pemahaman bahwa hasrat tersebut tak sepenuhnya milik kita seorang.34
Untuk mencapai kebijaksanaan tersebut kita perlu menyadari ketidakrelevansian kita, sesuatu yang sama dengan laku bunuh diri fenomenologis. Kosong takkan pernah menjadi sesuatu dengan melepaskan ketiadaan yang mendasari keberadaannya, sama seperti kata pepatah, semua orang ingin masuk surga, tetapi tak ada seorang pun yang ingin mati begitu saja.
Bagi Oughourlian, histeria tak selalu merupakan sebuah “penyakit klinis”, tetapi bisa saja sebuah kesalahpahaman tentang relasi antar individu, sebuah konflik mimetik, sebuah manifestasi fenomenologis atas suatu hasrat berikut usaha koping ataupun pemuasannya. Kesadaran atas kondisi mimetik kita memerlukan pemikiran fundamental mengenai subjektivitas dan hasrat. Lepas dari pemahaman umum kita, penyangkalan atas otonomi kemanusiaan berarti pelepasan atas segala kenikmatan yang mungkin saja kita alami saat kita menjadi boneka yang dikendalikan oleh mekanisme tersembunyi tersebut.
Persaingan-persaingan selalu berulang, kekambuhannya adalah suatu pengulangan mimetik. Persaingan mereproduksi dirinya sendiri, menduplikasi dirinya sendiri, menirukan kondisi-kondisi saat ia pertama kali terjadi dan selalu mengarah pada kemenangan yang mustahil tercapai—mustahil karena kesemuanya tumbuh dari kondisi-kondisi kekalahan. Kondisi-kondisi itulah hal terpenting bagi persaingan, setiap perebutan kemenangan adalah permainan keniscayaan kekalahan.
Sisifus jauh lebih beruntung dibandingkan kita, tiada lagi dewa-dewa yang menentukan batas absolutas serta menjaga relasi wajar antara individu dalam konteks mimetik. Girard mempelajari sejarah dan menemukan dua macam mediasi persaingan mimetik, eksternal dan internal.
Mediasi eksternal umumnya terjadi pada masyarakat berbasis kelas, di mana diferensiasi sosial menjadi pembatas bagi hasrat mimetik dan dimensi-dimensi konfliktual. Selama mediasi eksternal tersebut berjalan, model dapat berperan sebagai “penghambat” yang efektif bagi perkembangbiakan hasrat mimesis dan potensi terjadinya persaingan murni.
Sebaliknya, mediasi internal merupakan penanda suatu masyarakat egalitarian di mana konflik mimetic cenderung diselesaikan lewat persaingan langsung antara model dan subjek/imitator, berpotensi memicu kekerasan tak berkesudahan baik fisik maupun simbolis saat para anggotanya tak cukup siap menghadapi gejolak mimesis ataupun tak saling mawas diri.35
Keberhasilan mediasi eksternal bergantung pada ketiadaan komunikasi langsung, spasial maupun temporal, di antara para aktor sosial. Petaka akan terjadi manakala hirarki sosial runtuh dan memberi jalan bagi berkembangnya pilihan-pilihan saat jarak metafisik antara subjek dan model berkurang ataupun hilang sama sekali, semakin kecil/samar jarak tersebut, semakin besar pula potensi di mana mimesis akan berakhir dengan persaingan penuh kekerasan.36
Saat jarak sosial antar individu berkurang, proses imitasi mutual pun membesar. Pada masyarakat modern, transisi dari mediasi eksternal menuju internal cenderung memperkuat ilusi individu bahwa ia memiliki hasrat yang unik, otonom, dan sepenuhnya personal sementara perbedaan antar individu pun perlahan menghilang. Semua merasa layak membandingkan diri dengan yang lain ataupun menginginkan sesuatu yang orang lain miliki.37
Mekanisme kambing hitam adalah obat politik dalam versi Girard untuk kegagalan mediasi eksternal, ketidakmampuan suatu komunitas membendung luapan krisis mimetetik sehingga memerlukan suatu kambing hitam, entitas lain yang bisa dikorbankan untuk memutus mata rantai perkembangbiakan replikan. Proses subtitusi tersebut melahirkan efek pemutusan lewat pertentangan biner antara masyarakat dan kambing hitam, mekanisme politik-ekonomi yang turut mendorong tumbuhnya kebencian, pondasi fenomenologis atas moralitas borjuis, atau dengan kata lain, bentuk politik yang paling modern.
Hal paling mendasar dari konsumerisme adalah kita semua dapat menggantikan posisi satu sama lain lewat akumulasi dan penambahan nilai atas keberbedaan. Bagi konsumen modern, kebencian adalah suatu simtom pembusukan mediasi mimetik internal. Kesemuanya tumbuh dari ilusi kebebasan tak terbatas dalam konteks mimetik, suatu emosi invasif yang menggempur ruang publik dan kehidupan personal.38 Disjungsi antara waktu fisik dan waktu psikologis membuat masyarakat tampak lebih individualistis, kebencian dan individualisme pada masyarakat modern adalah relasi timbal balik yang terjadi secara mimetik.
“Orang-orang berimajinasi memiliki hasrat autentik dan personal sementara pada kenyatannya selalu ada mediator atas kemunculan keinginan-keinginan baru. Keinginan terus dilebih-lebihkan melalui kombinasi paradoksal antara peningkatan persaingan antar individu dan melebarnya ketimpangan sosial. Pada akhirnya sebagian besar subjeknya hanya memperoleh kutukan ketidakpuasan fundamental yang mendorong nafsu syahwat membabi buta.”39
Menurut Max Scheler, kebencian adalah proses keracunan mental yang terjadi secara swakarsa40, hasil dari represi menahun atas aspek-aspek emosional yang penyangkalannya menimbulkan suatu obsesi mimetik atas nilai-nilai sosial. Sebagaimana dosa atas sepuluh perintah Allah, Scheler mengikuti jejak Musa dan Nietzsche dalam menggambarkan kebencian sebagai usaha berekspresi yang sepenuhnya natural melalui antitesis kewarasan sosial. Dorongan pembalasan dendam mungkin adalah sumber dari munculnya kebencian, terakumulasinya segala macam perasaan yang berawal dari rasa iri, kedengkian, dan amarah yang tak terkendali.
Lepas dari karakter maupun pengalaman masing-masing individu, potensi kebencian dalam masyarakat kapitalis terakumulasi dengan sendirinya oleh struktur susial. Persaingan bebas bagi Scheler adalah versi fenomenologis dari kapitalisme yang dibayangkan Marx sebagai pengganti kontraktual atas relasi natural antar individu.41 Rasa iri bukan sekedar frustasi yang timbul dari keinginan atas suatu objek maupun komoditas, tetapi juga pada persaingan tak terkendali atas modal sosial yang akhirnya menghasilkan suatu kecemburuan eksistentinsial.
Karena sifatnya yang eksistensial dan bukan materialistis, rasa iri cenderung menghambat dorongan akuisitif alih-alih memperkuatnya. Akibatnya sering kali fatal, menyuburkan kebencian impoten di mana hal yang didamba-dambakan seolah mustahil dicapai—terkungkung dalam dimensi di mana kita terus membandingkan diri dengan liyan. Lebih lanjut, kedengkian eksistensial ini sering kali tertuju pada aspek paling natural liyan dan bekerja secara mimetik menyerupai kekerasan yang menular.
Girard menggambarkan modernitas sebagai proses universaliasi mediasi internal. Secara kolektif kita kehilangan privasi eksistensial dan menimbulkan suatu konstruksi di mana kepercayaan dan identitas menjadi sesuatu yang sepenuhnya mimetik. Sepanjang sejarah, kebencian cenderung subur di kalangan orang-orang yang melayani dan didominasi zaman42, menjerumuskan mereka dalam kubangan kebencian tanpa hasil pada kekuasaan dan otoritas.
Untuk menjelaskan rasa iri dan kedengkian, Girard melepaskan fokus dari objek yang dipersaingkan menuju si pesaing itu sendiri, menjadikannya awal mula sekaligus kesimpulan dalam analisis yang ia lakukan. Lantas, apakah kehendak untuk membalas dendam merupakan hal yang sejak dahulu kala mendominasi eksistensi dan hubungan manusia? Girard menjawabnya dengan menggambarkan bagaimana kekuatan kekerasan, baik fisik maupun simbolis, tertaut erat dalam penyebarannya. Mungkin pembalasan paling memuaskan bagi pelaku pembunuhan adalah terbunuhnya pembunuh tersebut, pada akhirnya tidak ada lagi perbedaan jelas antara perbuatan yang membuat si pembunuh dihukum serta hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Pembalasan dendam adalah sesuatu yang tak berujung pangkal, kejahatan yang menjadi sasarannya pasti bukanlah suatu pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya.43
Lalu apakah awal mulanya, kengerian macam apa yang terjadi sebelumnya. Kesemuanya adalah mimesis, sesuatu yang menciptakan kita, atau proses yang membuat kita tercipta, sesuatu yang secara paradoksal menjadi hambatan utama bagi kita untuk menjadi nyata maupun relevan sepenuhnya.
Melupakan amnesia, memulihkan ingatan akan ketidakcukupan manusia, memunculkan dorongan pembalasan dendam terhadap realitas yang membuat kita tak relevan dan setiap keinginan atas sebuah absolutas pastilah berakhir dengan tragis. Untuk menyadari bahwa seseorang takkan bisa menutup jarak antara dirinya yang tak relevan dengan rival dan model yang relevan adalah dengan memahami bahwa model tersebut sama sekali bukanlah hal yang dapat dicapai; dus model tersebut menjadi sebuah perintang.44 Akan tetapi, sejarah mencatat pula bagaimana rival mimetik tak melulu merupakan perintang mimetik pula, terlebih saat perintang mimetik tersebut ada karena suatu mediasi eksternal.
“Saat harus menghadapi rintangan, rival yang sejak dahulu ada, suatu kodrat yang tak dapat diatasi, sikap paling normal adalah dengan meninggalkan persaingan dan mengarahkan kembali hasrat yang ia rasakan secara lebih konstruktif (antagonistik?) serta dengan memahami batasan individual sekaligus batas-batas yang ditentukan oleh struktur sosial. Penyangkalan adalah pondasi dari setiap masyarakat hirarkis, pelepasan diri dari keduniawian yang menandai ketidakmungkinan suatu keinginan. Mediator keinginan selalu eksternal, bahkan ia selalu berada di hadapan kedua matamu.”45
Kabar baiknya, media massa telah mengubah semua itu. Di bawah konsumerisme, kebebasan direduksi menjadi pilihan-pilihan. Lewat kacamata Girard, ilusi konsumerisme dan iklan adalah bagaimana kesemuanya sekedar mendorong kita untuk menginginkan sesuatu, tetapi menghipnotis kita secara kolektif untuk percaya bahwa kita semua benar-benar individualistis meski menginginkan suatu hal yang sama. Iklan yang terpersonalisasi, kooptasi dan mimesis ganda atas konsepsi identitas, dan lusinan trik lainnya. Lewat cara-cara tersebutlah kapitalisme dapat menghambat kiamat total dari krisis hilangnya keberbedaan dalam masyarakat termutakhir. Ilusi kebebasan melalui konsumsi menutupi ketololan kita atas kemustahilan autentisitas.
Realitas integral Baudrillard terhubung dengan persaingan mimetik Girard melaui reversibilitas antara model dan citra, yang mana keduanya ditandai dalam lingkungan sosial kita oleh ide dan gagasan maupun meme-meme. Bagi Baudrillard, penanda utama dalam proses transisi dari kapitalisme menuju kapitalisme akhir dan kemudian kapitalisme pascakemanusiaan, adalah penggantian mode produksi industrial tradisional yang bersifat berurutan, oleh produksi-konsumsi yang didorong dan dikendalikan oleh hegemoni tontonan-tontonan. Bagi Girard, hegemoni tersebut pada dasarnya adalah ilusi atas objek libidinal dari segala macam hasrat, sesuatu yang anehnya tak pernah ada sama sekali dan tak pernah orisinal. Hasrat kita sudah pasti palsu karena kesemuanya adalah milik liyan. Dalam media sosial, meme merupakan hal yang dapat menggambarkan semuanya dengan sempurna; sebagai gambar elektronik yang terus beredar tanpa henti, ia menggambarkan model yang dibayangkan Baudrillard; sirkulasinya yang abadi menandai keberadaannya dan orang yang menciptakannya menjadi model dalam versi Girard.
Setelah kehadiran Facebook, jalan untuk membuktikan relevansi kita bukan lagi dengan menunjukan anterioritas hasrat yang kita rasakan, sesuatu yang tentu saja mustahil dan tolol, tetapi dengan memanfaatkan demokrasi media sosial media sebagai templat di mana kita menghadirkan diri sebagai model lewat sirkulasi meme. Hebatnya lagi, kini kita tak lagi dibatasi spektrum komunitas tradisonal, tetapi terintegrasi dalam komunitas unibersal yang menciptakan kesengkarutan relasi mimetik mahadahsyat yang belum pernah sebelumnya terjadi dalam riwayat manusia.
Baik Girard maupun Oughoularian belum sempat memikirkan secara tuntas dilema mimetik yang saat ini kita hadapi di media sosial. Kita terbiasa mengunggah persona kita sebagai suatu model untuk menunjukkan relevansi kita, dengan melakukan hal tesebut kita melewati sebuah depersonalisasi menuju integrasi pemusnahan virtual, semakin luas model tersebut tersebar, semakin tak nyata pula citra/gambaran yang diungkapkannya. Suatu meme tak pernah dimiliki siapa pun, ekslusivitas kepemilikan dan kepenciptaanya otomatis lenyap saat ia dilahirkan.
Hal paling mengerikan dari peredaran meme-meme di media sosial adalah keberadaanya yang menyerupai mekanisme kambing hitam Girard serta kekerasan simbolis. Dorongan pembalasan dendam Girard merupakan kembaran mimetik dari apa yang dibayangkan Nietche sebagai kekembalian abadi—keserupaan yang terus kembali dan terulang adalah imitasi dari kekosongan arkais yang kini terus berputar secara virtual.
Kita sungguh beruntung saat ini, baik Gustika Hatta maupun anak pegawai rendahan yang kuliah di suatu universitas swasta gurem sama-sama bisa menikmati BTS Meal, anak tukang becak pun mungkin saja bisa membeli BTS Meal, tidak ada yang mungkin hari ini, toh saat ini hampir semua orang punya smartphone dan memiliki akun media sosial entah di platform apa pun itu. Meski berkubu-kubu, setidaknya saat ini kita lebih mudah berkomunikasi dan menyepakati sesuatu, menyepakati akar permasalahan ataupun biang kerok dari suatu petaka misalnya. Aktivitas mimetik dalam media sosial dan media elektronik yang saling bertaut satu sama lain terhubung oleh ketidakcukupan kesemuanya atas realitas, kita semua butuh realitas, kita menginginkan kenyataan, setiap detik dan menitnya kita harus punya akses pada realitas termutakhir.
Jenaka sekali bagaimana semakin tak nyata sesuatu, semakin kuat pula potensi mimetiknya. Saat ini meme-meme terus beredar, sebagian mati dan monster baru terlahir bermutasi dari tumpukan bangkai mereka. Sebuah piktograf neoprimitif yang melampaui segala macam batas sosial.
Tentu saja berlebihan bila esai ini harus mencuri kesempatan rekan-rekan untuk mengingat kembali dan terus membayangkan kegilaan Girardian macam apa yang kelak bisa saja terjadi di era media sosial kini. Lagipula sulit rasanya bila harus menuliskan kengerian-kengerian yang sekiranya relevan dengan omong kosong ini tanpa harus mengulang kembali skenario Hobbes serta propaganda Darwin yang terus dikembangkan sejak masa Victoria.
Mari kembali saja pada kesibukan kita sehari-hari, mari bersama-sama lakukan sesuatu yang serupa dan mungkin saja suatu saat nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Gulir terus, mungkin saja apa yang selama ini kita cari dan dambakan ternyata ada di dasar linimasa.
Jean Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, trans. Ian Grant, 1993, 16
Jean Baudrillard, The Divine Left , trans. David L. Sweet, 2014 , 42
Jean Baudrillard, The Agony of Power, trans. Ames Hodges, 2010, 35
Jean-Michel Oughourlian, The Genesis of Desire, trans. EugeneWebb, 12
René Girard, Violence and the Sacred, trans. Patrick Gregory, 1977,145
Girard, Things Hidden Since the Foundation of the World, 161
René Girard, The One by Whom Scandal Comes, trans. M. B. De Boise, 2014, 104–5.
Jean-Michel Oughourlian, The Mimetic Brain, trans. Trevor Cribben Merrill, 2016, 38
Oughourlian, The Genesis of Desire, 98. Bayangkan, aku merasakan hasrat maka aku ada
Wolfgang Palaver, René Girard’s Mimetic Theory, trans. Gabriel Borrud, 2013, 25
Stefano Tomelleri, Reflections on Mimetic Desire and Society, 2015, 92–93
Max Scheler, Ressentiment, trans. Lewis B. Coser & William W. Holdheim, 2010, 25.