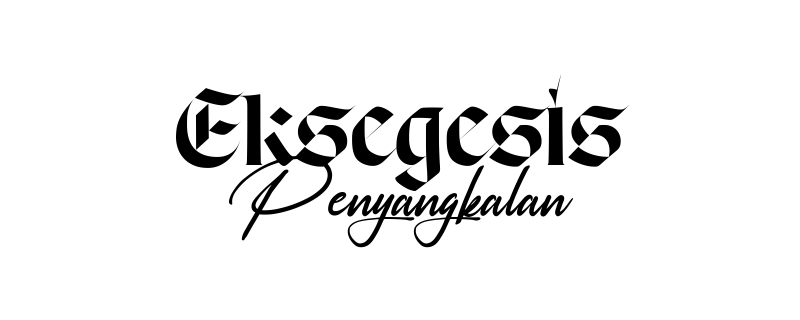
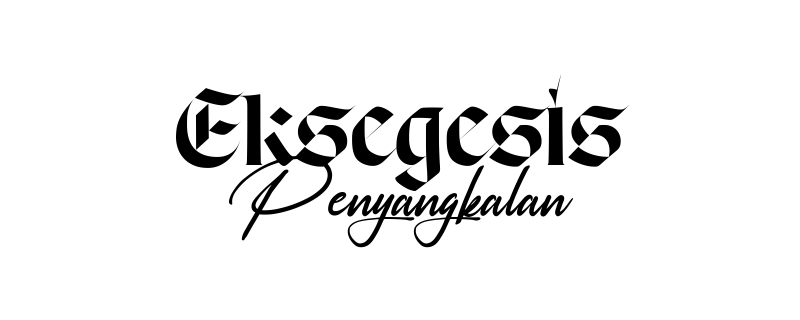
Teks sebagai gerak—relasi yang timbul antara penulis, gestur, dan konten diekspresikan melalui bermacam tingkat deklinasi berbeda pada bidang vital gerakan. Oleh karena itu, piranti semiotik selalu melekat pada citra serta konstruksi perseptif para aktor sosial yang terlibat dengannya. Kata-kata hadir sebagai perantara dalam afirmasi historis untuk mempertahankan relevansinya lewat simbol-simbol, dari perwujudan paleolitiknya menuju bentuk yang lebih modern. Dalam konteks kontemporer, pemisahan yang dibayangkan McLuhan antara tanda, citra, dan suara lebur ditelan pendekatan transmedial dengan vitalitas yang lebih besar, terputus-putus oleh hilangnya kontinuitas dalam pemisahan spasial tersebut—kali ini, dengan sensasi gerak yang jauh lebih besar.
Matriks gerak tersebut merupakan perwujudan hasrat dalam berbagai deklinasinya. Setiap elemen bahasa berdenyut berputar dalam beragam tautan, hubungan, dan konjungsi yang menjauhkan para subjek dari asal-usul matrilinealnya. Dalam hal ini, kita tidak sedang bergulat dengan sebuah dalih rasional melainkan hasrat primordial untuk berekspresi.
Dari modalitas hipo-komunikasi menuju hiper-komunikasi, rasa frustasi terus menguat membisukan setiap emosi manusia dengan membaurkan segala macam respon menjadi sesuatu yang sepenuhnya logis dan intelektual. Hasrat dipaksa objektif menjadi bagian proses pengungkapan, demistifikasi, dan segala macam konsekuensinya. Media massa memodifikasi tubuh manusia menjadi triptych Freud-Lacan-McLuhan dengan menghadirkan informasi sebagai proses amplifikasi ekstrim dari cerminan eksistensi maternal manusia di mana media hadir mendampinginya sebagai sosok keibuan.
Aktor sosial terbius proyeksi pencitraan dirinya sendiri yang hadir bersama sejumlah elemen kesadaran. Torsi psikososial yang dihasilkan dalam proses tersebut mengungkap bentuk komunikasi terputus-putus dalam proyeksi eksistensi kita, sebagaian besar karena gempuran informasi dan sebagian lainya oleh segala sesuatu yang tak berhasil dicukupinya. Dalam proses ini, liyan terkikis menghilang sehingga kecenderungan atas pengulangan segala sesuatu yang bersifat intim, personal, maupun kolektif pun hanya dapat muncul ke permukaan secara tak menentu, penuh ketegangan, neurotik, sekaligus konyol, atau dengan kata lain, secara konfliktual.
Saat ini media massa hadir sebagai pemutusan hubungan kita dengan liyan, berawal dari Rimbaud lalu Lacan, bahasa tergelincir jatuh dalam gangguan komunikasi. Hubungan sosial kini menjadi sebuah privilese, tergagap dalam lompatan paradigmatik dari suatu sikap sosial satu menuju yang lain, menangguhkan setiap potensi aktor sosial untuk menjadi subjek sejarah, membenamkan relasi sosial dalam fluiditas imaterial yang mengaburkan tujuan serta kesadaran kolektif masyarakat.
Berbagai jenis ekspresi mengenai hal tersebut di atas dapat kita temukan dengan mudah dalam bahasa puitis, yang subversif dan dibesarkan oleh jurnalisme serta pemasaran, ataupun yang disalahgunakan begitu saja menuju banal dan nirmakna. Kesemuanya merupakan sisa-sisa kesenangan orgasmik yang perlahan terlupakan, segala yang berdenyut menggempur batas-batas identitas maupun bagian kesadaran badaniah yang melampaui konsepsi korporeal—sebagai kursi penuh privilese dalam pentas komunikasi maupun ekspresi artistik.
Kata-kata ditumbukkan begitu saja pada halaman buku-buku, bahasa menjadi remukan. Struktur semantik atas keberadaan liyan yang sepenuhnya terbalik hadir sebagai titik nol di mana setiap pengalaman individu atas realitas maupun dirinya sendiri disorongkan menuju ribuan pemberhentian serta permulaan.
Penulisan adalah hasrat tak terbendung atas bahasa, bentuk tertulis dari kebulatan tekad dan bukan sisa-sisanya, pondasi atas peradaban yang imperatif sekaligus represif. Sebuah konsepsi keanehan milik Freud dan segala yang menganggu, sesuatu yang belum muncul, sesuatu yang tersembunyi sekaligus begitu dekat.
Hal tak dikenal yang dihadirkan sebagai praktik menulis maupun menerjemahkan. Segala yang aneh, terlihat jelas dalam gestur bahasa yang familiar namun tersembunyi. Teramat familiar karena ada dalam diri dan lingkungan terdekat kita, menganggu karena berlabuh dalam pengalaman sensasional yang sama sekali tak dapat diakses dengan mudah.
Pada akhirnya tak ada jalan lain, tak ada pilihan, tak ada tujuan maupun tempat untuk kembali.
Hanya ada fantasi atas kesenangan yang telah lama hilang, bahasa yang terdemagnetisasi maujud kembali sebagai artikulasi sejarah yang sama sekali berbeda, hasrat yang bergolak dalam bisu yang menjangkiti teks maupun penuturan.
Bahasa artistik sebagai suatu praktik penyalahgunaan kata-kata, reruntuhan monumen keterasingan manusia, muntahan yang menjadi kontraksi estetis, residu orgasmik, hedonisme, dan kemubaziran.
Akan datang eksegesis penyangkalan, sebuah pemahaman bahasa yang belum sepenuhnya paripurna, bahasa yang tak terpoles, bahasa yang terbuang, bahasa tanpa tendensi, bahasa yang mengabaikan batas kesadaran serta segala sesuatu yang bergolak di bawahnya. Bahasa yang tertulis sebagai letupan, bahasa yang tak lengkap dan tak sempurna. Bentuk baru komunikasi yang sepenuhnya berlabuh pada matriks kesengkarutan. Teknik penulisan yang terlontar terempas menuju pengekspresian hasrat sebagai medium yang berpegang pada kontak komunikasi dialektis atas dorongan liar bahasa yang sepenuhnya impulsif. Otomatis bagaikan mesin dan primitif layaknya binatang.